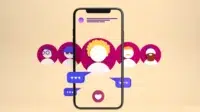Globalisasi yang telah membawa perubahan besar dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dunia. Melihat fenomena ini tidak hanya mempercepat pertukaran informasi dan barang, akan tetapi juga memperdalam ketimpangan dan memperkuat dominasi kapitalisme global.
Melihat konteks tersebut, warisan pemikiran Frankfurt School menjadi sangat relevan untuk menelaah dinamika globalisasi dan kritik sosial yang menyertainya (Suhaeb & Ismail, 2023). Frankfurt School yang muncul pada awal-awal abad ke 20 merupakan kelompok pemikir yang pemikir yang berfokus pada hubungan antara budaya, masyarakat, dan ekonomi.
Dengan mengembangan teori sosial kritis yang bertujuan untuk memahami dan mengkritik berbagai struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Di Dalam konteks globalisasi, pemikiran mereka memberikan kerangka analisis yang mendalam untuk mengeksplorasi dampak sosial dan budaya dari sebuah fenomena ini (Garlitz & Zompetti, 2023).
Dilihat dari globalisasi dan pertukaran budaya menjadi salah satu dampak yang paling cocok dari globalisasi yaitu pertukaran budaya yang semakin cepat. Masyarakat di seluruh dunia kini dapat mengakses berbagai bentuk seni, musik, dan tradisi dari belahan dunia lain, akan tetapi Frankfurt School mengingatkan kita bahwa pertukaran ini sering kali tidak seimbang, yang dimana budaya menjadi dominan terutama dari negara-negara barat lebih cenderung mengesampingkan dan menggerus pada budaya lokal (Sholahudin, 2020).
Dalam sebuah konteks budaya, pada pemikiran Adorno dan Horkheimer tentang industri budaya menawarkan wawasan dan pengetahuan mendalam mengenai bagaimana produk-produk budaya di bawah sistem kapitalisme berfungsi sebagai alat komodifikasi.
Baca Juga: Peran Filsafat Ilmu dalam Mencari Kebenaran yang Hakiki
Mereka berpendapat bahwa budaya seharusnya menjadi sarana ekspresi dan sebuah kreatifitas yang telah terdistorsi menjadi sebuah barang dagangan yang diproduksi massal. Hal ini mengarah pada hilangnya sebuah nilai-nilai otentik dan spontanitas yang seharusnya ada dalam sebuah karya seni dan budaya (Klaudia BR Semimbing, 2021).
Logika industri budaya ini semakin diperkuat oleh globalisasi yang mempercepat penyebaran budaya populer yang homogen. Ketika sebuah produk budaya dari berbagai belahan dunia dibawa ke pasar global. Bahwa kita sering melihat dominasi beberapa budaya pasar seperti budaya besar yang menggeser keberagaman budaya lokal.
Akibatnya, banyak sekali budaya lokal yang terpinggirkan dan terancam punah karena tidak mampu bersaing dengan arus budaya populer yang lebih mudah diakses dan lebih menarik bagi konsumen. Dengan melihat proses ini juga memunculkan pada sebuah fenomena “konsumerisme budaya” yang dimana individu lebih tertarik pada sebuah citra dan pengalaman superficial dari pada sebuah makna yang mendalam dari budaya itu sendiri.
Produk budaya yang dihasilkan bukan sekedar barang yang dibeli dan dikonsumsi dan bukan sesuatu yang dihargai dan dihayati. Akan tetapi, menciptakan pada kesenjangan antara pengalaman budaya otentik dan apa yang dipasarkan sebagai budaya dalam konteks industri (Prakoso, 2020).
Dalam perspektif ini, paling penting untuk menyadari bahwa dampak negatif dari homogenisasi budaya akibat kapitalisme dan globalisasi. Dengan itu masyarakat perlu berupaya untuk melestarikan keberagaman budaya lokal dan mencari cara untuk mengintegrasikan pada sebuah nilai-nilai yang autentik ke dalam sebuah produk budaya yang diproduksi.
Hanya dengan cara inilah kita dapat menciptakan sebuah ruang yang inklusif yang dimana berbagai bentuk ekspresi budaya dapat berkemabang dan dihargai tanpa terjebak dalam logika komodifikasi yang merugikan.
Dalam analisisnya Adorno dan Horkhaimer menyoroti bahwa industri budaya berfungsi sebagai alat manipulasi massa yang sangat efektif. Mereka berpendapat bahwa produk budaya mulai dari film, musik, hingga televisi diproduksi dengan tujuan utama yang dijual, bukan untuk mengedukasi atau memberdayakan.
Pada proses ini menimbulkan homogenisasi nilai-nilai budaya dimana variasi dan keragaman diabaikan demi keuntungan ekonomi. Ketika budaya dipandang sebagai komoditas, kualitas artistik dan kreatifitas sering kali dikorbankan demi menarik pada perhatian konsumen.
Baca Juga: Ibnu Rusyd: Ketika Akal dan Wahyu Bertemu dalam Harmoni
Lebih jauh lagi, Adorno dan Horkheimer mengemukakan bahwa industri budaya tidak hanya memproduksi pada sebuah barang. Tetapi, juga menciptakan yang terstandarisasi. Dalam dunia yang dipenuhi dengan iklan dan promosi, konsumen diajak untuk menganggap produk-produk budaya sebagai kebutuhan yang esensial.
Hal ini mengarah pada penciptaan identitas yang dangkal, yang di mana individu merasa terikat pada merek atau produk tertentu, meskipun sebenarnya mereka hanya menjadi bagian dari sebuah mesin kapitalis yang lebih besar. Manipulasi ini juga bertujuan untuk menumpulkan pemikiran kritis masyarakat.
Orang-orang cenderung mengabaikan masalah sosial dan politik yang lebih mendalam ketika mereka fokus pada hiburan yang disajikan oleh industri budaya. Menurut Adorno dan Horkheimer, cerita dalam budaya populer sering mengalihkan perhatian dari ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial.
Dengan kata lain, hiburan berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan keadaan saat ini sehingga masyarakat tidak diingatkan untuk mempertanyakan struktur kekuasaan yang sudah ada.
Dalam hal ini, globalisasi adalah faktor utama yang mendorong homogenisasi budaya.
Baca Juga: Gagasan dan Pemikiran Politik Kartosuwirjo
Dengan akses yang semakin mudah ke produk budaya global, masyarakat dihadapkan pada pilihan yang tampaknya lebih banyak, tetapi sebenarnya terkurasi oleh kepentingan pasar. Karena konsumen lebih memilih produk yang dianggap lebih “modern” atau “trendy”, budaya lokal yang kaya akan nilai-nilai dan tradisi seringkali tertinggal.
Hal ini tidak hanya membahayakan budaya lokal, tetapi juga memperkuat dominasi budaya tertentu, yang dapat mengikis identitas nasional. Menurut Adorno dan Horkheimer, industri budaya menciptakan ilusi kebebasan. Konsumen merasa memiliki kebebasan untuk memilih, tetapi pilihan mereka terbatas pada pilihan pasar.
Dalam situasi di mana orang merasa terjebak dalam siklus konsumsi, mereka cenderung mengabaikan kemungkinan untuk membuat pilihan yang lebih penting dan signifikan. Ini menyebabkan fenomena di mana orang lebih suka bertahan dengan apa yang mereka miliki daripada mencoba mengubahnya.
Penulis: Bara ‘Izza Lawahizh
Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka
Dosen Pengampu: Rita Pranawati
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Daftar Pustaka
Garlitz, D., & Zompetti, J. (2023). Critical theory as Post-Marxism: The Frankfurt School and beyond. Educational Philosophy and Theory, 55(2), 141–148. https://doi.org/10.1080/00131857.2021.1876669
Klaudia BR Semimbing. (2021). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 10(1), 6.
Prakoso, B. (2020). Tren Budaya Industri Pada Lagu Didi Kempot : Perspektif Teori Kritis Trend of the Culture Industry on Didi Kempot ’ S Song : a Critical Theory Perspective. Orasi : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 11(1), 15–34.
Sholahudin, U. (2020). Membedah Teori Kritis Mazhab Frankfurt : Sejarah, Asumsi, Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Teori Ilmu Sosial. Journal of Urban Sociology, 3(2), 71. https://doi.org/10.30742/jus.v3i2.1246
Suhaeb, F. W., & Ismail, A. (2023). Identitas Budaya di Era Globalisasi. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), 7(3), 2598–9944. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5240/https
Ikuti berita terbaru di Google News