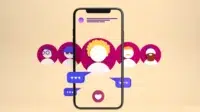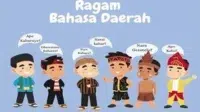Realitas yang Mengusik Nurani
Pagi itu di kelas, saya melihat seorang siswa tertidur di atas lengan. Saat dibangunkan, ia berkata lirih, “Maaf, Pak. Semalam, saya kerja sampai jam sebelas.”
Kalimat itu menyadarkan saya bahwa tidak semua siswa datang dengan kondisi fisik dan mental yang siap belajar.
Di balik seragam, mereka menyimpan kisah perjuangan yang tidak selalu terlihat. Saya mengajar di sebuah SMA negeri di Kecamatan Sungai Apit, pesisir Kabupaten Siak, Riau.
Beberapa siswa saya bekerja sepulang sekolah—sebagai buruh kebun, pengantar barang, penjaga warung, atau membantu usaha keluarga.
Meskipun dilakukan di luar jam sekolah, dampaknya terasa di ruang kelas: kelelahan, konsentrasi menurun, dan motivasi belajar yang fluktuatif.
Data BPS (2024) mencatat bahwa 2,8% anak usia 10–17 tahun di Indonesia bekerja, dan di Riau angkanya mencapai 2,11%, mayoritas di daerah perkebunan dan pesisir.
Ini bukan fenomena langka, tetapi realitas harian banyak siswa. Mereka hadir di kelas, tapi tidak selalu dalam kondisi utuh—fisik maupun psikis.
Mereka hidup dalam dua dunia: dunia sekolah yang menuntut disiplin, dan dunia nyata yang menuntut kedewasaan sebelum waktunya.
Pendidikan tidak boleh sekadar menuntut, tetapi juga memahami dan menyesuaikan diri dengan kenyataan hidup peserta didik.
Di balik absensi dan nilai rapor, ada ketabahan dan keberanian yang tidak bisa diukur dengan angka.
Dampak Psikologis dan Akademik
a. Kesiapan Belajar yang Terganggu
Siswa yang bekerja sambilan sering datang ke sekolah dalam kondisi sangat lelah.
Kurang tidur menyebabkan mereka mengantuk di kelas dan sulit berkonsentrasi.
Akibatnya, pemahaman materi menurun dan mereka tertinggal dalam tugas.
Keterlambatan bahkan ketidakhadiran juga sering terjadi, memperburuk kesiapan belajar mereka.
Menurut teori Cognitive Load (Sweller, 1988), otak manusia memiliki kapasitas terbatas untuk menerima informasi baru.
Jika kapasitas itu telah terkuras oleh pekerjaan fisik dan stres, maka belajar jadi semakin berat.
b. Tekanan Sosial dan Psikologis
Selain kelelahan fisik, siswa ini juga menghadapi tekanan psikologis.
Mereka cemas tertinggal pelajaran, merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi ekspektasi guru, dan akhirnya menarik diri dari lingkungan sosial. Beberapa memilih diam atau bersikap apatis.
Dalam fase remaja, menurut Erikson (1968), individu seharusnya membentuk identitas diri. Namun, beban hidup yang berat membuat proses ini terganggu.
Mereka merasa tidak cukup baik dan kehilangan arah, baik secara akademik maupun sosial.
c. Dorongan Ekonomi dan Motivasi Konsumtif
Dorongan ekonomi memang menjadi alasan utama siswa bekerja, tetapi ada pula faktor konsumtif: keinginan memiliki gadget, ikut tren, atau memperoleh pengakuan sosial.
Lingkungan pergaulan dan media sosial memperkuat tekanan ini.
Menurut Maslow (1943), kebutuhan dasar seperti rasa aman dan pengakuan sosial harus terpenuhi sebelum individu bisa mencapai aktualisasi diri, termasuk dalam konteks belajar.
Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, motivasi belajar pun melemah.
d. Tantangan Guru dan Sekolah
Dalam situasi ini, guru dan sekolah tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan seragam.
Pendekatan Funds of Knowledge (Moll et al., 1992) mengajarkan bahwa pengalaman hidup siswa—seperti bekerja di warung atau kebun—bisa menjadi sumber belajar yang berharga.
Misalnya, siswa bisa diberi tugas berbasis proyek sesuai latar belakang mereka: menghitung pendapatan warung untuk pelajaran matematika, membuat laporan pasar untuk pelajaran ekonomi, atau membuat video promosi untuk pelajaran bahasa.
Selain itu, sekolah bisa berkolaborasi dengan masyarakat agar siswa mendapat pekerjaan yang lebih ramah terhadap waktu belajar.
Guru pun perlu dilatih dalam pedagogi yang responsif dan berempati, termasuk pendekatan trauma-informed.
Fleksibilitas jam belajar dan ruang konseling juga menjadi kebutuhan nyata dalam konteks ini.
Ajakan untuk Pendidikan yang Empatik dan Adaptif
Kehidupan sosial siswa makin kompleks. Memahami latar belakang mereka kini menjadi tanggung jawab moral dan profesional guru.
Pertemuan saya dengan siswa yang tertidur karena bekerja hingga larut malam menunjukkan bahwa belajar tidak terjadi di ruang hampa.
Ada tekanan hidup, tuntutan ekonomi, dan rasa tidak aman yang ikut menentukan kesiapan belajar.
Sekolah harus menjadi tempat yang fleksibel, suportif, dan manusiawi. Tidak semua siswa bisa diperlakukan dengan pendekatan seragam.
Harus ada kelonggaran waktu, pendekatan individual, dan sistem dukungan psikososial yang aktif menjangkau.
Refleksi bagi guru sangat penting: apakah kita hanya mengajar, atau benar-benar mendidik? Apakah kita menghukum keterlambatan, atau mencari tahu apa yang terjadi?
Data BPS hanyalah angka di atas kertas—tapi di lapangan, mereka adalah wajah-wajah yang kita temui setiap hari.
Konsep pembelajaran mendalam (Marton & Säljö, 1976) menekankan pemaknaan materi dan keterkaitannya dengan kehidupan nyata.
Namun, bagaimana mungkin ini terjadi jika rasa aman dan kepercayaan diri siswa belum terbentuk?
Teori Maslow juga menegaskan bahwa aktualisasi belajar hanya bisa terjadi jika kebutuhan dasar terpenuhi.
Artinya, kebijakan pendidikan harus adaptif. Kurikulum tidak boleh menjadi beban, tetapi harus menjadi alat untuk memahami dan menguatkan siswa.
Fleksibilitas waktu, diferensiasi pembelajaran, serta ruang yang inklusif dan adil harus menjadi bagian dari sistem.
Sekolah harus menjadi tempat yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan.
Penulis: Indra Wahyudi
Mahasiswa Magister Pedagogi, Universitas Lancang Kuning
Dosen Pengampu: Dian Nasrah Marisa, PhD
Referensi
Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2024.
Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis.
Marton, F., & Säljö, R. (1976). On qualitative differences in learning: I—Outcome and process. British Journal of Educational Psychology, 46(1), 4–11.
Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review.
Moll, L. C., Amanti, C., Neff, D., & Gonzalez, N. (1992). Funds of Knowledge for Teaching: Using a Qualitative Approach to Connect Homes and Classrooms. Theory into Practice, 31(2), 132–141.
Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. Cognitive Science, 12(2), 257–285.
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News