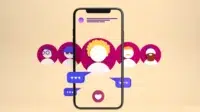Perjalanan di pulau Jawa, kini pilihannya beragam. Sebelum era Ignasius Jonan, kereta api menjadi pilihan terakhir. Ada banyak suka dan cita menggunakan kereta di zaman itu. Penjual makanan dan minuman yang silih berganti naik-turun. Bisa menikmati kuliner berbagai kota yang dilewati.
Bahkan sesekali dapat naik kereta Malang-Jakarta, tanpa perlu beli tiket. Duduknya di WC atau jutru di gerbong terakhir. Dimana ada space yang dapat digunakan untuk duduk. Atau juga space antar gerbong.
Selama perjalanan barang-barang perlu dijaga dengan super ketat. Kalau gagal, bonusnya bisa berupa kehilangan barang setiba di tujuan. Dalam satu keempatan, perjalanan Jakarta-Surabaya, seorang penumpang kehilangan jam tangan.
Sementara di belakangnya, seorang mahasiswa percasarjana yang kehilangan laptop. Keduanya sekalipun melapor ke bagian pengamanan, tetap saja tak tertolong sama sekali.
Akhirnya, sang mahasiswa tetap saja menggunakan kereta dan disertai trauma yang berkepanjangan. Laptop yang sudah tergantikan, kemudian dipegang erat selama dalam kereta. Takut untuk kehilangan sekali lagi.
Trauma itulah yang dibawanya sampai ke pelbagai negara. Ketika dengan kereta apapun, tetap saja laptop dipegang dan dijaganya dengan sepenuh hati. Takut untuk kehilangan.
Tapi itu, cerita dulu. Sekarang, sekali lagi perjalanan kereta api menjadi pilihan utama. Menyenangkan, sejuk, dan tentu saja aman. Masuk ke stasiun untuk boarding, menggunakan KTP atau pengenal yang sudah teregistrasi di tiket sejak pembelian.
Termasuk pembelian tiket yang dapat diakses melalui lokapasar dan aplikasi lainnya. Sehingga beli tiket, tidak lagi harus ke stasiun kereta. Kalaupun mau ke sana, tetap juga ada loket yang juga aman dan nyaman. Tidak ada lagi calo yang sibuk menawarkan jasa dan kadang lebih mudah mendapatkan tiket berbanding di loket dimana tiket sudah diborong calo.
Inilah buah dari reformasi. Kesempatan kita mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Dimana ketika Jonan menjadi direktur Kereta Api Indonesia (KAI) memprakarsai terobosan. Kata kawan saya semalam dalam percakapan warung kopi, revitaliasi kereta jarak jauh dilaksanakan terlebih dahulu karena itu lebih ringan.
“Saat mengelola sebuah proyek perubahan yang ringan dan jikalau saja gagal, tidak akan beresiko besar. Berbanding sebuah proyek yang berat,” kata kawan di sela-sela pertemuan warung kopi.
Apa yang dicapai Jonan, tentu bukanlah pekerjaan seorang saja. Ada Sofyan Djalil yang mau menjadikannya sebagai direktur. Kemudian Dahlan Iskan dalam posisi jabatan mentri BUMN meneruskan apa yang telah dimulai Djalil.
Ini dapat diartikan bahwa perlu ada kepercayaan dalam ssebuah tim kerja. Di saat kepercayaan itu disertai dalam sebuah mandat, maka akan menghasilkan buah kerja dan kinerja yang berdampak bagi banyak orang. Maka, kunci untuk mendapatkan transformasi selain soal mandat adalah juga kepercayaan yang mengiringi mandat tersebut.
Dalam satu cerita Jonan di tahun 2015 saat penyerahan anugerah Tata Wahana Nusantara di Kemenhub bahwa inovasi toilet yang awalnya kotoran jatuh ke bawah gerbong kereta sehingga menjadi kotoran di sepanjang rel, diubah dengan biaya yang ekonomis. Peneliti di INKA mendapati biaya sampai 500 juta.
Sementara pegawai KAI, cukup dengan biaya 12 juta. Itupun ditemukan oleh seorang pegawai dengan kualifikasi sarjana hukum. Fakta ini juga dikemukakan ketika obrolan terkait dengan jabatan menteri. Seorang kawan yang menyampaikan aspirasi untuk menjadikan seorang guru besar pertanian menjadi menteri pertanian.
Lalu ditimpali bahwa jabatan menteri sejatinya adalah posisi politis. Bukanlah pekerja teknis ataupun memerlukan kepakaran tertentu. Bahkan, kita dapat melihat bahwa Menteri Kesehatan tidaklah harus seorang dokter.
Apa yang diprakarsai Jonan bersama tim, akhirnya dinikmati bersama. Menunggu boarding ke Kereta Brawijaya tujuan kota Malang, di samping tempat duduk saya juga ada wisatawan asing yang berpasport Belanda dalam hitungan jari sebuah tangan yang bersiap juga naik kereta.
Bahkan di stasiun Gambir, juga tersedia toko buku. Bagian yang menarik, toko buku dengan status toko buku “resmi” menjual buku yang resmi pula. Bukan buku bajakan yang ada dijual tak jauh dari Gambir, pasar Senen dimana ada gerai yang menjajakan buku-buku bajakan.
Sehingga saat memilih sebuah buku untuk dibeli, sayapun mengecek jangan sampai itu adalah buku bajakan. Sang pemilik kios menjawabnya dengan memastikan bahwa tokonya adalah agen resmi dari sebuah toko buku.
Akhirnya, dua buku berpindah tangan yang disertai bonus. Menemani perjalanan antara stasiun Gambir ke stasiun Kota Malang.
Satu hal lagi, pembajakan buku menjadi perhatian Tere Liye. Melalui pelbagai platform media sosial, dan bahkan dalam halaman buku yang ditulisnya juga tersedia peringatan terkait dengan masalah buku bajakan ini.
Olehnya, masalah ini merupakan suara penulis yang juga menjadi tugas bersama pembaca. Soal buku bajakan akan menjadi masalah tersendiri dalam urusan membangun ekosistem perbukuan. Hanya tukang photo copy sajalah yang untung.
Sementara penulis, distributor, dan toko buku, akan perlahan hilang dan lenyap.
Terakhir, soal transformasi diawali dari kegelisahan. Dimana ada masalah yang menjadi kegelisahan bersama. Sehingga perlu diambil tindakan untuk menangani. Kalau itu selesai, lagi-lagi akan membawa dampak luas. Tidak saja soal ekonomi belaka, namun akan menjadi sebuah tumpukan keyakinan bahwa kita bisa.
Penulis: Ismail Suardi Wekke
Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat Daya