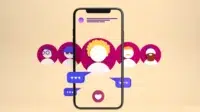Lagu trending yang tahun 2025 berjudul Garam dan Madu (Sakit Dadaku) adalah lagu bergenre hiphop dangdut atau “hipdut” yang pertama kali viral besar di awal tahun 2025. Lagu ini dinyanyikan oleh tiga sosok yang langsung mencuri perhatian yakni Tenxi, Jemsii, dan Naykilla.
Tenxi adalah rapper sekaligus produser muda yang sebelumnya dikenal lewat remix trap-Jawa di SoundCloud. Sementara Jemsii rekan duetnya mempunyai gaya vokal khas yang menyeimbangkan unsur hiphop dan soul. Rekan duet perempuan bernama Naykilla, yang tak lain adalah adik dari penyanyi Sara Fajira dapat membawa sentuhan melodius dan nuansa dangdut koplo modern ke dalam lagu.
Ketiga penyanyi ini menciptakan kombinasi unik antara bahasa Jawa, Indonesia, dan Inggris dalam liriknya, menyentuh tema patah hati dan cinta penuh konflik (Musik Kapan Lagi, 2025).
Perpaduan beat trap, rhythm dangdut, dan pengaruh urban menjadikan Garam dan Madu tidak hanya viral di TikTok, tapi juga mencetak rekor streaming di Spotify dan Youtube. Lagu ini pun diakui sebagai simbol gelombang baru musik Indonesia yang melebur batas genre, budaya, dan generasi (Setyawan, 2023).
Fenomena viralnya lagu hiphop dangdut Garam dan Madu (Sakit Dadaku) sebagai tren di media sosial TikTok dapat dibaca sebagai medan kontestasi dalam bingkai Cultural Studies terutama ketika menyoroti hegemoni identitas, kelas, dan kuasa dalam lanskap budaya populer digital Indonesia.
Pada relasi kekuasaan, genre hipdut itu sendiri merupakan bentuk hibriditas budaya yang memadukan elemen musik rakyat (dangdut) dengan ekspresi urban kontemporer (hiphop dan trap).
Namun, dalam penggabungan tersebut juga terdapat resistensi terselubung hipdut menjadi arena di mana ekspresi kelas bawah (melalui nada-nada dangdut koplo) tidak hanya bertahan, tetapi malah dikemas ulang dan menembus dominasi selera kelas menengah atas, terutama di platform seperti TikTok.
Pada ruang lingkup diskursus media dan produksi makna, TikTok berperan penting sebagai medium yang tidak netral (Tanjung, 2025). Berdasarkan algoritma tidak hanya menyebarkan konten, tetapi juga mengonstruksi apa yang dianggap relatable, trending, atau aspiratif oleh publik muda.
Lagu Garam dan Madu menyebar bukan semata karena nadanya catchy, melainkan karena ia masuk ke dalam rezim representasi emosional yang diinginkan oleh audiens Gen Z yakni patah hati, identitas labil, dan ekspresi diri.
TikTok menjadi ruang produksi makna baru, tempat musik menjadi lebih dari sekadar hiburan, tapi bagian dari narasi identitas digital yang bisa dinegosiasikan ulang melalui challenge, lip-sync, dan remix. Sementara aspek identitas dan representasi, Garam dan Madu menghadirkan keragaman simbolik.
Tenxi sebagai produser muda dari daerah (Sidoarjo) merepresentasikan desentralisasi kuasa produksi musik dari Jakarta sebagai pusat industri, Jemsii membawa suara laki-laki urban dengan gaya vokal soul yang emosional, dan Naykilla menampilkan performativitas feminin yang sensual sekaligus kuat memunculkan diskusi tentang gender performativity dan posisi perempuan dalam musik populer.
Di balik itu, ada pembacaan kelas yakni suara-suara “pinggiran” baik secara geografis maupun ekonomi dapat menembus mainstream melalui estetika digital yang dikurasi dengan strategi algoritmik.
Musik ini menjadi wacana visual sekaligus audio tentang politik identitas, di mana genre musik tidak lagi netral, melainkan sarat penanda tentang siapa yang berbicara, dari mana, dan untuk siapa (Yunindar, 2025).
Pada dimensi emansipatoris dan potensi perubahan sosial, hipdut membuka kemungkinan bagi pembalikan hierarki kultural. Musik ini tidak sekadar menghibur, tetapi memberi ruang legitimasi bagi ekspresi-identitas yang selama ini dianggap rendah, kampungan, atau tak layak masuk arus utama.
TikTok menjadi “ruang publik mikro” tempat pergeseran nilai itu berlangsung secara organik, dengan partisipasi jutaan pengguna yang secara aktif memproduksi ulang simbol dan narasi.
Baca Juga: Tren ‘GRRR’ di TikTok: Antara Hubungan Hiburan, Kreativitas, dan Tantangan Literasi Digital
Fenomena dari hipdut tidak hanya menjadi genre musik baru, tetapi juga praktik budaya yang disruptif, yang menawarkan kemungkinan resistensi terhadap hegemoni selera dominan dan membayangkan ulang konfigurasi sosial-budaya dalam lanskap digital Indonesia.
Hal ini menjadi contoh hegemoni kultural Gramscian sebagai kekuasaan dominan (wacana musik “modern” dan “urban”) tidak secara langsung menindas budaya lokal, tetapi mengakomodasinya dalam format baru yang terasa “keren” bagi kalangan muda.
Hegemoni menurut Antonio Gramsci (1971) merupakan konsep sentral dalam analisis relasi kuasa dalam masyarakat kapitalis, yang merujuk pada bentuk dominasi yang tidak hanya berbasis pada kekuasaan koersif (paksaan fisik atau hukum), tetapi terutama pada persetujuan aktif masyarakat terhadap tatanan sosial yang berlaku.
Gramsci membedakan antara dominasi (yang bersifat paksaan) dan hegemoni (yang bersifat persetujuan), serta menekankan bahwa hegemoni bersifat dinamis dan harus terus diperjuangkan.
Pada setiap tatanan hegemonik, terdapat ruang resistensi, karena kelompok-kelompok subordinat bisa mengembangkan “kesadaran kritis” (consciousness) yang menjadikan untuk menolak ideologi dominan dan membentuk apa yang disebut Gramsci sebagai “hegemoni alternatif” yakni bentuk kepemimpinan ideologis baru yang dapat menantang status quo (Mauluddin, 2023).
Pada kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci (1971), fenomena viralnya lagu Garam dan Madu (Sakit Dadaku) dapat dibaca sebagai ekspresi dominasi ideologis yang beroperasi melalui budaya populer.
Lagu ini memiliki perpaduan genre hiphop dangdut atau hipdut, menampilkan bentuk hegemonik baru di ranah musik digital, di mana selera budaya dominan yakni musik urban global seperti trap dan hiphop berhasil mengakomodasi elemen-elemen lokal seperti dangdut koplo dan bahasa Jawa.
Proses ini mencerminkan apa yang disebut Gramsci sebagai hegemonisasi budaya, yakni bagaimana kelas atau kelompok dominan tidak memaksakan nilai-nilainya secara terang-terangan, melainkan memasukkannya ke dalam bentuk-bentuk yang dapat diterima oleh kelompok subordinat, sehingga tercipta konsensus kultural.
Praktik budaya dalam lagu Garam dan Madu (Sakit Dadaku) merefleksikan sekaligus mempertahankan dan pada saat yang sama menantang struktur kekuasaan dan ideologi yang berlaku dalam industri musik serta masyarakat digital kontemporer.
Lagu ini merefleksikan dominasi ideologi kapitalisme digital dan estetika global, di mana musik diproduksi untuk viralitas, daya jual, dan kompatibilitas algoritmik di platform seperti TikTok dan Spotify.
Baca Juga: Apakah Kita Mengonsumsi TikTok atau TikTok yang Mengonsumsi Kita?
Penggabungan elemen hiphop, trap, dan dangdut meskipun tampak sebagai inovasi tetap berada dalam bingkai selera populer yang dibentuk oleh struktur kuasa budaya dominan.
Penggunaan bahasa Inggris dan gaya produksi urban oleh artis seperti Tenxi dan Jemsii menunjukkan norma-norma global tetap mendikte bentuk ekspresi lokal, mempertahankan relasi kuasa antara pusat (barat, urban) dan pinggiran (lokal, tradisional).
Namun, di sisi lain, praktik ini juga memiliki potensi menantang struktur tersebut. Dengan menempatkan elemen lokal seperti dangdut koplo, bahasa Jawa, dan identitas musisi dari luar pusat industri ke ruang dominan digital, lagu ini memperluas representasi dan membongkar batas antara yang “rendah” dan yang “tinggi”, yang “kampungan” dan yang “keren”.
Representasi Naykilla sebagai perempuan muda dengan suara dan visual yang kuat juga memberi ruang renegosiasi terhadap narasi maskulin dalam genre hiphop.
Maka, praktik budaya ini bersifat dialektis dengan mempertahankan hegemoni melalui format yang sesuai dengan selera dominan, tetapi juga menjadi ruang artikulasi alternatif bagi identitas dan ekspresi yang selama ini terpinggirkan dalam lanskap budaya populer Indonesia (Luh dkk., 2025).
Refleksi kritis terhadap fenomena lagu hiphop dangdut seperti lagu Garam dan Madu (Sakit Dadaku) menunjukkan bahwa budaya populer digital tidak terlepas dari relasi kuasa dan dominasi ideologis.
Meskipun tampak sebagai ekspresi kebebasan kreatif, praktik ini tetap berada dalam logika pasar dan algoritma media sosial yang membentuk selera massa. Namun demikian, terdapat potensi emansipatoris apabila praktik budaya ini dimaknai secara kritis sebagai ruang artikulasi identitas alternatif.
Sebagai rumusan tindakan praksis, perlu dikembangkan literasi media yang mendorong kesadaran kritis terhadap representasi dan produksi makna, serta dukungan terhadap ekosistem kreatif lokal yang otonom dari hegemoni industri budaya global. Oleh sebab itu budaya populer dapat menjadi sarana resistensi simbolik dan transformasi sosial (Kadir, 2025).
Penulis: Rizalif Bagus Bintang SA
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dosen Pengampu: Dr. Merry Fridha Tri Palupi, M.Si.
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Daftar Pustaka
https://musik.kapanlagi.com/berita/viral-di-tiktok-ini-lirik-dan-makna-lagu-garam-dan-madu-6987a24.html diakses pada 5 Juli 2025
Kadir, Z. K. (2025). Kriminologi Reaksioner: Sayap Kanan, Moralitas, Dan Kriminalisasi Budaya Pop Dalam Era Post-Truth. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2(5), 10108–10121.
Luh, N., Esa, M., Erviantono, T., & Noak, P. A. (2025). Politik Tubuh Perempuan Antara Kontrol Sosial dan Resistensi. Socio-Political Communication and Policy Review, 2(3), 1–12.
Mauluddin, A. (2023). Relasi Hegemoni Dan Demokrasi Antonio Gramsci. Research Gate, December. https://doi.org/10.1007/978-3-658-
Setyawan, A. (2023). Sounding Indonesia, Indonesians Sounding: A Compendium of Music Discourses (Issue March 2023). https://doi.org/10.6084/m9.figshare.28720868.v1
Tanjung, M. A. (2025). TikTok Sebagai Ruang Dialog Kultural Generasi Z dan Tradisi Lokal. Journal of Mandalika Social Science, 3.
Yunidar, M. (2025). Bahasa, Budaya, dan Masyarakat: Perspektif Sosiolinguistik Kontemporer. Kaizen Media Publishing.
Ikuti berita terbaru di Google News