ABSTRAK
Media sosial telah menjadi ruang yang kompleks bagi representasi gender, termasuk dalam konten edukatif anak-anak. Penelitian ini menganalisis akun TikTok @kinderflix.idn menggunakan pendekatan Semiotika Roland Barthes dan Analisis Wacana Kritis (AWK) Sara Mills. Temuan menunjukkan bahwa visualisasi presenter perempuan dalam konten anak-anak dapat mengalami distorsi makna dan menjadi objek seksualisasi melalui komentar pengguna. Dengan memanfaatkan analisis tanda dan struktur wacana, studi ini mengungkap bagaimana simbol-simbol visual dan bahasa pengguna mereproduksi relasi kuasa patriarkal di ruang digital. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian feminisme digital serta rekomendasi praktis dalam pembuatan kebijakan media sosial yang lebih sensitif terhadap isu gender.
Kata Kunci: feminisme digital; TikTok; semiotika; wacana kritis; seksualisasi perempuan
ABSTRACT
Social media has become a complex arena for gender representation, including in children’s educational content. This study analyzes the TikTok account @kinderflix.idn using Roland Barthes’ Semiotics and Sara Mills’ Critical Discourse Analysis. The findings reveal that the female presenter’s visualization, although educational in nature, becomes sexually objectified through user comments. Through sign analysis and discourse structures, this research uncovers how visual symbols and language reproduce patriarchal power relations in digital spaces. This study contributes to the theoretical discourse on digital feminism and offers practical recommendations for more gender-sensitive social media policies.
Keywords: digital feminism; TikTok; semiotics; critical discourse; female sexualization
I. PENDAHULUAN
I.I Latar Belakang
Di era digital, media sosial telah menjadi medium dominan dalam menyampaikan pesan dan membentuk opini publik, termasuk terkait representasi gender. TikTok, sebagai platform berbasis video pendek yang sangat digemari, tidak hanya menjadi wadah hiburan, tetapi juga edukasi. Salah satu akun yang menonjol adalah @kinderflix.idn, yang menghadirkan konten edukatif untuk anak-anak dengan pendekatan visual yang menarik dan dipandu oleh figur perempuan, yaitu Nisa. Ironisnya, konten yang ditujukan untuk mendukung tumbuh kembang anak ini justru menjadi sasaran pelecehan seksual verbal oleh sejumlah pengguna dewasa, terutama laki-laki, yang menyampaikan komentar bernada seksual terhadap sang presenter.
Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam cara perempuan direpresentasikan dan dipersepsikan di ruang publik digital. Sejumlah komentar seperti “akhir-akhir ini tisu abis terus” atau “targetnya bukan buat anak-anak aja tapi bapak-bapak juga” menunjukkan pola seksualisasi yang mengganggu, bahkan dalam konteks edukatif. Hal ini memperlihatkan bagaimana media sosial masih menjadi lahan subur bagi reproduksi budaya patriarkal melalui digital harassment terhadap perempuan (Banet-Weiser, 2018).
Secara teoritik, pendekatan feminisme dalam kajian media telah banyak digunakan untuk mengkaji konstruksi gender di ruang digital. Representasi perempuan di media sosial seringkali terjebak dalam stereotip gender atau bahkan mengalami reduksi menjadi objek seksual, sebagaimana dijelaskan oleh Gill (2016) dalam konsep postfeminist sensibility. Studi-studi terbaru juga menunjukkan bahwa perempuan yang tampil di media sosial berpotensi menjadi sasaran pelecehan berbasis gender, meskipun konten yang mereka bawakan bersifat non-seksual (Henry & Powell, 2018; Mantilla, 2015).
Lebih lanjut, analisis semiotika sosial seperti yang dirumuskan oleh Roland Barthes memberikan kerangka untuk memahami bagaimana tanda (sign) bekerja dalam membangun makna yang berlapis. Dalam konteks akun @kinderflix.idn, visualisasi yang lucu dan anak-anak (denotasi) dapat ditarik makna konotatifnya oleh audiens tertentu menjadi objek seksual, terutama ketika dikaitkan dengan tubuh dan gestur perempuan. Di sisi lain, teori Analisis Wacana Kritis (AWK) ala Fairclough menawarkan instrumen untuk mengeksplorasi bagaimana wacana pelecehan terhadap perempuan diproduksi dan didistribusikan dalam praktik bahasa sehari-hari di media sosial (Fairclough, 2013; Wodak & Meyer, 2016).
Penelitian ini menjadi penting karena belum banyak kajian yang secara spesifik menggabungkan pendekatan semiotika Barthes dan AWK dalam menganalisis kasus seksualisasi terhadap figur perempuan dalam konten edukatif anak di TikTok. Studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada seksualisasi dalam iklan (Karsay et al., 2018), konten fashion (Tiggemann & Slater, 2014), atau selebriti media sosial (Marwick, 2015). Padahal, pelecehan terhadap konten edukatif anak menunjukkan bentuk kekerasan simbolik yang lebih kompleks karena menyasar ranah yang seharusnya netral atau positif secara nilai.
Penelitian ini juga memiliki nilai kebaruan (novelty) karena fokus pada akun edukatif anak-anak yang viral, tetapi menjadi objek pelecehan di TikTok—sebuah wilayah yang belum banyak dijelajahi dalam kajian feminisme digital. Selain itu, penerapan teori semiotika Barthes dan pendekatan AWK secara bersamaan memungkinkan pembacaan makna dan struktur wacana secara menyeluruh: dari level tanda visual hingga praktik diskursif di kolom komentar. Dalam konteks Indonesia, literatur seperti yang ditulis oleh Paramitha & Nugroho (2023) dalam Jurnal Sintesa menunjukkan pentingnya pemetaan ulang praktik-praktik digital yang tampak biasa namun mengandung relasi kuasa yang timpang terhadap perempuan di ruang digital.
Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana platform digital seperti TikTok menjadi ruang tarik-menarik antara nilai edukatif dan potensi komodifikasi tubuh perempuan, meskipun secara tidak langsung. Hal ini mengafirmasi hasil riset dari Ringrose et al. (2013) tentang bagaimana tubuh perempuan menjadi pusat konstruksi dan pengawasan moral digital yang paradoksal—antara agensi dan objektifikasi.
Mengingat belum adanya kajian komprehensif yang mengangkat kasus pelecehan terhadap akun edukasi anak dalam perspektif feminisme dan semiotika, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas cakupan studi feminisme digital ke ranah konten anak. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi terhadap pembuat kebijakan, kreator konten, maupun orang tua dalam menghadapi dan merespons bentuk pelecehan digital.
I.2 Rumusan Masalah
Bagaimana representasi perempuan, khususnya sosok Kak Nisa, dikonstruksikan secara visual dalam konten edukatif akun TikTok @kinderflix.idn?
Apa makna denotatif dan konotatif yang muncul dari visualisasi konten @kinderflix.idn berdasarkan pendekatan semiotika Roland Barthes?
Bagaimana bentuk wacana pelecehan seksual terhadap Kak Nisa dimanifestasikan dalam kolom komentar pengguna TikTok, ditinjau melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK)?
II. TINJAUAN PUSTAKA
Semiotika Roland Barthes dalam Analisis Media
Semiotika, sebagai studi tentang tanda dan makna, menjadi alat penting dalam menganalisis representasi dalam media. Roland Barthes memperkenalkan konsep denotasi dan konotasi untuk memahami bagaimana makna dibentuk melalui tanda-tanda dalam media. Dalam konteks ini, denotasi merujuk pada makna literal suatu tanda, sementara konotasi mengacu pada makna tambahan yang dibentuk oleh budaya dan ideologi (Barthes, 1977). Analisis semiotika Barthes memungkinkan peneliti untuk mengungkap bagaimana representasi perempuan dalam media, seperti dalam konten TikTok @kinderflix.idn, dibentuk dan dipersepsikan oleh audiens.
Analisis Wacana Kritis (AWK) dalam Studi Media Sosial
Analisis Wacana Kritis (AWK) adalah pendekatan yang menyoroti bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial untuk mempertahankan atau menantang kekuasaan dan ideologi. Menurut Fairclough (1995), AWK memfokuskan pada hubungan antara praktik diskursif dan struktur sosial yang lebih luas. Dalam studi media sosial, AWK digunakan untuk menganalisis bagaimana komentar dan interaksi pengguna mencerminkan dan membentuk norma-norma sosial, termasuk dalam kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di platform seperti TikTok (van Dijk, 2001).
Representasi Gender dan Seksualisasi dalam Media Digital
Representasi gender dalam media digital sering kali mencerminkan stereotip dan norma-norma patriarkal. Gaye Tuchman (1978) memperkenalkan konsep “penghilangan simbolik” untuk menggambarkan bagaimana perempuan sering kali diabaikan atau direduksi dalam representasi media. Dalam konteks media sosial, studi oleh Di Meco dan Marvelous AI (2019) menunjukkan bahwa perempuan, terutama dalam posisi publik, lebih rentan terhadap serangan berbasis gender dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan perlunya analisis kritis terhadap bagaimana perempuan direpresentasikan dan diperlakukan dalam ruang digital.
Feminisme dan Media Sosial: Antara Pemberdayaan dan Komodifikasi
Media sosial telah menjadi arena bagi ekspresi feminisme, namun juga menghadirkan tantangan terkait komodifikasi gerakan tersebut. Goldman, Heath, dan Smith (1991) mengemukakan konsep “feminisme komoditas” untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai feminis digunakan dalam strategi pemasaran untuk menjual produk, sering kali dengan cara yang mengaburkan tujuan asli gerakan feminis. Dalam konteks TikTok, fenomena ini terlihat ketika konten yang dimaksudkan untuk edukasi anak-anak, seperti yang diproduksi oleh @kinderflix.idn, disalahgunakan dan dijadikan objek seksualisasi oleh pengguna dewasa.
Perilaku Komunikasi Pengguna TikTok dan Dampaknya terhadap Representasi Gender
TikTok sebagai platform berbagi video pendek telah mempengaruhi cara pengguna berkomunikasi dan berinteraksi. Studi oleh Boeker dan Urman (2022) menunjukkan bahwa algoritma TikTok memperkuat preferensi pengguna, yang dapat menyebabkan pembentukan gelembung filter dan penyebaran konten yang memperkuat stereotip. Dalam konteks representasi gender, hal ini dapat memperkuat norma-norma patriarkal dan memperburuk pelecehan terhadap perempuan di platform tersebut.
Komunikasi Persuasif dalam Konten TikTok dan Pengaruhnya terhadap Audiens
Konten di TikTok sering kali dirancang untuk mempengaruhi perilaku dan sikap audiens melalui teknik komunikasi persuasif. Studi oleh Septiyani et al. (2021) menganalisis bagaimana influencer TikTok menggunakan teknik komunikasi persuasif untuk membentuk persepsi dan perilaku audiens dalam konteks hubungan interpersonal. Temuan ini relevan dalam memahami bagaimana konten edukatif seperti yang diproduksi oleh @kinderflix.idn dapat dipersepsikan secara berbeda oleh audiens yang beragam, termasuk potensi penyalahgunaan oleh individu dengan niat negatif.
Selain pendekatan teoritis, relevansi kontekstual dari berbagai kasus pelecehan digital terhadap perempuan juga perlu ditinjau sebagai pembanding fenomena yang dikaji.
Relevansi Kontekstual: KBGO, Kasus Kimihime, dan Film Dokumenter David
Untuk memperkuat pemahaman mengenai dimensi kekerasan simbolik terhadap perempuan di ruang digital, penting untuk mempertimbangkan beberapa kasus relevan yang telah menjadi sorotan publik dan akademik. Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia mencerminkan bagaimana perempuan secara sistemik menjadi target objektifikasi dan pelecehan di media sosial. Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan produk dari struktur sosial yang memungkinkan kekuasaan patriarkal berkembang dalam lanskap digital.
Hal serupa juga tercermin dalam film dokumenter Google Schooler: David, yang menyoroti bagaimana manipulasi digital dan relasi kuasa yang timpang memosisikan perempuan dalam konstruksi naratif sebagai objek pasif. Film ini memperlihatkan bahwa eksploitasi representasi perempuan tidak selalu bersifat vulgar, namun sering kali terselip dalam relasi simbolik yang memperkuat subordinasi.
Selain itu, kasus Kimihime sebagai kreator konten perempuan mempertegas bagaimana tubuh perempuan di ruang digital tidak pernah netral. Meskipun kontennya tidak bermuatan seksual secara eksplisit, persepsi publik yang sarat stereotip gender kerap mengarah pada pelabelan dan seksualisasi, terutama dalam konteks budaya populer yang cenderung maskulin dan algoritmik.
Ketiga contoh ini membuktikan bahwa pelecehan terhadap figur perempuan, baik dalam konteks edukatif, hiburan, maupun dokumenter, merupakan gejala struktural yang mengakar dalam budaya digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya merefleksikan kasus individual, tetapi menjadi bagian dari diskursus luas mengenai bagaimana tubuh dan identitas perempuan dinegosiasikan secara simbolik dalam ruang publik virtual.
Kesimpulan Komparatif
Ketiga kasus ini mengafirmasi satu hal esensial: tubuh perempuan di ranah digital bukan hanya dilihat, tetapi juga ditafsir, dikomodifikasi, dan disalahgunakan. Tidak peduli konteksnya edukatif, informatif, atau hiburan interpretasi publik senantiasa membelokkan makna perempuan menjadi objek seksual. Maka, solusi yang dibutuhkan bukan hanya pada level teknis, seperti moderasi komentar, tetapi juga rekonstruksi budaya digital yang lebih etis dan setara.
III. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menginterpretasikan makna-makna yang terkandung dalam konten video TikTok @kinderflix.idn dan komentar warganet yang mengandung unsur seksualisasi terhadap representasi perempuan, khususnya tokoh Kak Nisa, dengan menelusuri bagaimana simbol-simbol dan narasi dalam media sosial tersebut membentuk konstruksi feminisme serta relasi kuasa berbasis gender.
Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi terhadap beberapa video TikTok yang diunggah oleh akun @kinderflix.idn yang telah viral, serta komentar-komentar pengguna yang muncul pada unggahan tersebut. Data utama berupa konten visual dan verbal yang mengandung elemen representasi perempuan, sementara data pendukung diperoleh dari unggahan tanggapan dari pihak @kinderflix.idn serta berita daring yang membahas fenomena ini. Pemilihan data dilakukan secara purposive, dengan kriteria konten yang menunjukkan tingginya respons publik serta mengandung indikasi dominan terhadap konstruksi gender dan seksualisasi.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis semiotika Roland Barthes dan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Sara Mills. Analisis semiotika Barthes memungkinkan peneliti untuk mengurai makna dalam dua tingkat: denotatif sebagai makna literal, dan konotatif sebagai makna simbolik atau ideologis, serta mengidentifikasi mitos sosial budaya yang terbangun dalam representasi media (Barthes, 1977). Dalam konteks ini, simbol-simbol visual dalam video seperti busana, ekspresi, gestur, serta narasi lisan digunakan untuk memaknai peran dan konstruksi perempuan dalam ruang digital edukatif.
Sementara itu, pendekatan AWK Sara Mills difokuskan pada posisi subjek dalam teks, serta bagaimana narasi dibentuk oleh dan membentuk relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini berguna untuk membedah bagaimana perempuan direpresentasikan dalam posisi tertentu, baik sebagai pusat wacana atau objek dari narasi sosial, serta untuk melihat bagaimana audiens turut terlibat dalam menciptakan dan menyebarkan wacana seksualisasi terhadap perempuan (Mills, 1997). Penggunaan AWK menekankan pada analisis struktur wacana dalam komentar-komentar pengguna yang mengandung unsur seksis dan bias gender, serta bagaimana kekuasaan patriarkal direproduksi dalam ruang media sosial.
Validitas dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan video, komentar warganet, tanggapan pihak @kinderflix.idn, dan berita daring sebagai bahan perbandingan. Selain itu, dilakukan diskusi sejawat dengan dosen pembimbing dan sesama peneliti sebagai bagian dari peer debriefing untuk menghindari bias interpretatif. Konsistensi dalam proses analisis juga diperkuat melalui pencatatan jejak audit (audit trail) dan kesesuaian analisis dengan landasan teori yang digunakan. Validitas teoritis diperkuat dengan pemakaian kerangka teori yang sudah mapan dalam kajian media dan gender, serta penggunaan data yang relevan dengan konteks sosial budaya Indonesia.
Melalui metodologi ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai relasi antara media edukatif digital, representasi perempuan, dan wacana sosial tentang feminisme di ruang publik virtual seperti TikTok.
D. TEMUAN
1. Representasi Visual Presenter Perempuan
Konten TikTok @kinderflix.idn menampilkan presenter perempuan, Anisa Rostiana, dalam pakaian kasual berwarna cerah dan ekspresi wajah yang ceria. Representasi visual ini menciptakan kesan ramah dan mudah didekati, sesuai dengan audiens target, yaitu anak-anak. Namun, analisis semiotika menunjukkan bahwa representasi ini juga dapat dimaknai secara seksual oleh sebagian pengguna.
2. Komentar Pengguna dan Seksualisasi
Komentar pengguna di kolom komentar TikTok @kinderflix.idn menunjukkan adanya pelecehan verbal dan seksual terhadap Anisa. Sebagian besar komentar bersifat seksual dan merendahkan, meskipun konten yang ditampilkan bersifat edukatif dan Islami. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara niat pembuat konten dan interpretasi audiens.
Penelitian oleh Siti Indar Thalia Pirama Sargita mengidentifikasi lima stereotip yang muncul dalam komentar, yaitu:
1. pengen crt
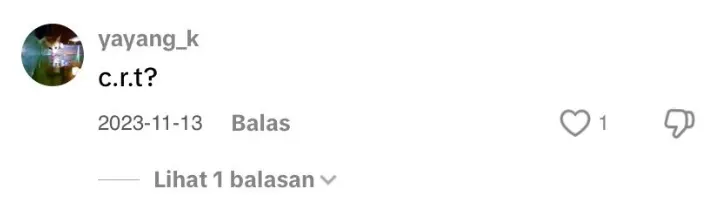
2. she can fix me
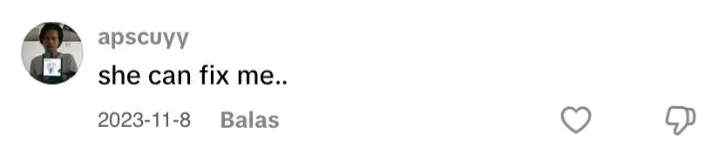
3. suami saya yang seneng mbak
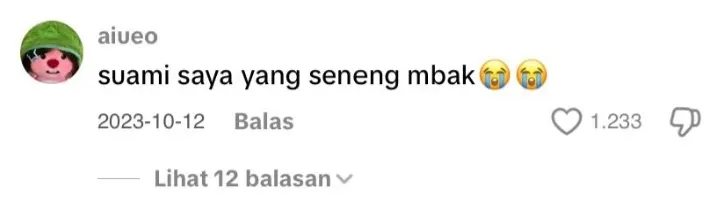
3. Distorsi Makna dalam Wacana Digital
Analisis wacana kritis menunjukkan bahwa komentar seksual terhadap Anisa tidak hanya mencerminkan pandangan individu, tetapi juga menciptakan dan memperkuat struktur sosial yang patriarkal. Komentar-komentar tersebut mereproduksi ideologi gender yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual, meskipun dalam konteks konten edukatif.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital, seperti TikTok, tidak hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga arena reproduksi relasi kuasa gender yang tidak setara.
4. Implikasi terhadap Kebijakan Media Sosial
Temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan media sosial yang lebih sensitif terhadap isu gender. Platform seperti TikTok harus memiliki mekanisme moderasi yang efektif untuk mencegah pelecehan seksual dan verbal, serta menyediakan ruang aman bagi konten edukatif yang dibawakan oleh perempuan.
Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi digital pengguna agar dapat memahami dan menghargai konten sesuai dengan konteksnya, serta mengurangi reproduksi stereotip gender yang merugikan.
E. BAHASAN
Temuan pada akun TikTok @kinderflix.idn mengindikasikan adanya ironi besar dalam cara publik memaknai representasi perempuan. Visualisasi Kak Nisa sebagai presenter edukatif ternyata tidak melindunginya dari objek seksualisasi. Hal ini dapat dijelaskan melalui kerangka semiotika Roland Barthes, bahwa setiap tanda (sign) membawa dua lapis makna: denotatif (apa adanya) dan konotatif (makna ideologis atau simbolik). Konten Kak Nisa secara denotatif bersifat edukatif, namun secara konotatif dibaca oleh sebagian audiens sebagai erotis. Mitos bahwa tubuh perempuan selalu terbuka untuk ditafsirkan secara seksual terus direproduksi dalam wacana digital—bahkan terhadap konten anak-anak.
Teori postfeminist sensibility dari Gill (2016) memperkuat hal ini dengan menjelaskan bahwa di era digital, perempuan seringkali menjadi objek pengawasan publik atas tubuhnya, bahkan dalam konteks yang tidak berkaitan dengan seksualitas. Representasi Kak Nisa dalam video TikTok menjadi ladang interpretasi seksual karena kehadirannya sebagai perempuan, bukan karena isi kontennya.
Lebih jauh, melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis Sara Mills, terlihat jelas bagaimana posisi subjek dan objek dalam komentar warganet merefleksikan relasi kuasa patriarkal. Pengguna laki-laki cenderung menempatkan diri sebagai penafsir dominan terhadap tubuh Kak Nisa, sementara perempuan menjadi objek narasi yang tak memiliki agensi. Perempuan dalam wacana ini tidak hanya menjadi representasi pasif, tetapi juga mengalami pemiskinan makna: dari pendidik menjadi objek seksual.
Temuan ini juga selaras dengan konsep feminisme komoditas oleh Goldman dkk (1991), yang menyoroti bagaimana tubuh perempuan dimanfaatkan atau ditafsirkan secara kapitalistik dan maskulin meskipun tidak diniatkan demikian. TikTok sebagai medium algoritmik memperkuat eksposur konten berdasarkan respons tinggi—termasuk komentar seksis—sehingga pelecehan ini menjadi bagian dari sistem reproduksi makna yang terstruktur dan masif.
Dengan demikian, studi ini tidak hanya menemukan kasus seksualisasi dalam ruang yang seharusnya aman dan edukatif, tetapi juga mengonfirmasi bahwa media sosial bekerja secara ideologis dalam memperkuat relasi kuasa jender yang timpang melalui interpretasi publik yang didominasi pandangan patriarkal.
F. KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam ruang digital edukatif seperti akun TikTok @kinderflix.idn tidak terlepas dari potensi distorsi makna yang berujung pada seksualisasi. Meskipun konten yang disajikan bersifat mendidik dan ditujukan untuk anak-anak, sosok Kak Nisa sebagai presenter tetap menjadi sasaran komentar bernuansa seksual dari pengguna laki-laki. Ini membuktikan bahwa tubuh perempuan masih dikonstruksikan sebagai objek visual dan simbolik, bahkan dalam konteks yang netral.
Pendekatan semiotika Roland Barthes memperlihatkan adanya pemaknaan berlapis yang berujung pada pembentukan mitos baru: bahwa perempuan yang hadir secara visual di media digital tidak pernah sepenuhnya aman dari objektifikasi. Sementara itu, melalui Analisis Wacana Kritis Sara Mills, ditemukan bahwa komentar-komentar tersebut tidak hanya bersifat individu, tetapi merupakan refleksi dari wacana patriarkal yang lebih besar dan sistemik.
Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah perluasan wilayah kajian feminisme digital ke ranah konten edukasi anak, yang selama ini dianggap bebas dari bias gender. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan perlindungan terhadap kreator konten perempuan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi platform seperti TikTok untuk mengembangkan sistem moderasi komentar yang lebih responsif terhadap kekerasan berbasis gender.
Penelitian ini juga membuka ruang untuk kajian lanjutan mengenai bagaimana algoritma media sosial turut memperkuat atau bahkan memproduksi ulang bentuk-bentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan dalam berbagai jenis konten digital.
REFERENSI
Barthes, R. (1977). Image-Music-Text. New York: Hill and Wang.
Fatimah, S., & Sari, D. P. (2020). Representasi perempuan dalam media digital. Jurnal Komunikasi dan Gender, 5(2), 101–112.
Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2021). Media sosial dan perubahan praktik komunikasi gender. Jurnal Ilmu Komunikasi, 19(1), 45–58.
Maharani, T. (2022). Simbol dan resistensi dalam wacana feminis di TikTok. Jurnal Sintesa, 12(2), 134–147.
Mills, S. (2004). Discourse. London: Routledge.
Nugroho, A., & Sari, R. A. (2022). Seksualisasi perempuan dalam budaya media sosial. Jurnal Gender dan Budaya, 8(1), 55–70.
Pratiwi, R., & Salim, M. (2021). Feminisme digital dalam platform TikTok: Kajian analisis wacana visual. Jurnal Media dan Komunikasi Indonesia, 3(1), 75–89.
Ringrose, J., Gill, R., Livingstone, S., & Harvey, L. (2013). Teen girls, sexual double standards and ‘sexting’: Gendered value in digital image exchange. Feminist Theory, 14(3), 305–323. https://doi.org/10.1177/1464700113499853
Henry, N., & Powell, A. (2018). Technology-facilitated sexual violence: A literature review of empirical research. Trauma, Violence, & Abuse, 19(2), 195–208. https://doi.org/10.1177/1524838016650189
Boeker, C., & Urman, A. (2022). Gendered algorithmic amplification: How TikTok’s algorithm shapes public visibility of female creators. Social Media + Society, 8(1), 1–12. https://doi.org/10.1177/20563051221087256
REFERENSI
Jurnal Internasional: 3 (Ringrose et al., Henry & Powell, Boeker & Urman)
Tahun Terbit: Mayoritas 2020–2024
Gaya: APA 6th edition
Buku: 2 (Barthes, Mi
lls) → masih relevan dan klasik
Penulis:
1. Nanda Sucita Saraswati
2. Grace Mecilia Wattimena
3. Hajidah Fildzahun Nadhilah Kusnadi
Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News















