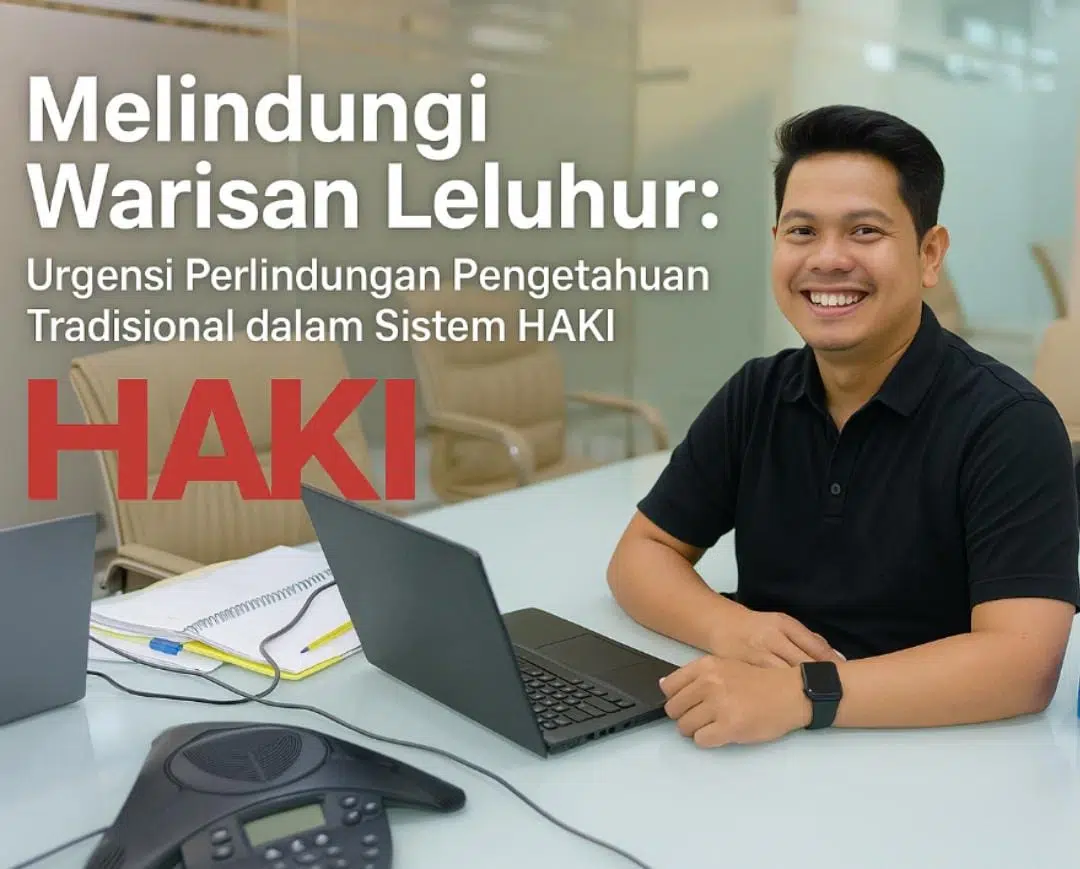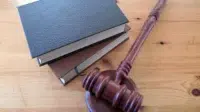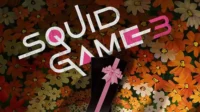Peduli Rakyat.co.id, Jakarta – Di balik kekayaan alam Indonesia yang luar biasa, tersimpan pula kekayaan tak ternilai dalam bentuk pengetahuan tradisional (PT).
Dari ramuan jamu nenek moyang hingga sistem pertanian subak di Bali, semua adalah hasil kecerdasan kolektif masyarakat lokal yang diwariskan turun-temurun.
Sayangnya, di era kapitalisme global dan dominasi paten multinasional, pengetahuan tradisional ini justru berada di ambang eksploitasi sering tanpa perlindungan hukum yang memadai.
Pertanyaannya, mengapa hingga hari ini pengetahuan tradisional di Indonesia belum terlindungi secara optimal dalam sistem hukum kekayaan intelektual (HAKI)? Dan apa implikasinya jika hal ini terus dibiarkan?
Baca juga: Proses Dinamis Terbentuknya Kebudayaan: Warisan, Inovasi, dan Tantangan Globalisasi
Warisan yang Terlupakan dalam Kerangka Hukum Formal
Dalam sistem HAKI konvensional, perlindungan hanya diberikan kepada invensi yang baru, individual, dan memiliki nilai ekonomi.
Pengetahuan tradisional, yang biasanya merupakan hasil kolaborasi komunitas dan telah eksis selama ratusan tahun, jelas tidak memenuhi kriteria ini.
Maka tidak heran jika ramuan obat tradisional, metode pengolahan hasil bumi, hingga pola tenun khas daerah, kerap “diambil alih” oleh pihak asing, modifikasi sedikit, lalu dipatenkan tanpa izin.
Kita tentu belum lupa kasus “biopiracy” atas temulawak dan jati belanda yang dipatenkan oleh perusahaan luar negeri.
Padahal tanaman itu tumbuh subur di Indonesia dan telah lama digunakan masyarakat lokal sebagai bahan pengobatan herbal.
Ironisnya, produk hasil paten itu justru dijual kembali ke Indonesia dengan harga tinggi.
Ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga soal moralitas dan keadilan.
Baca juga: Perlindungan Keanekaragaman Hayati Lingkungan Ditinjau dari Perspektif Hukum Lingkungan
Urgensi Payung Hukum: Mengangkat yang Lokal, Melawan yang Global
Indonesia sebenarnya sudah mulai mengambil langkah dengan mengesahkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memasukkan pengetahuan tradisional sebagai objek yang bisa dilindungi.
Namun, payung hukum ini masih bersifat deklaratif dan belum memiliki mekanisme perlindungan yang kuat dan implementatif.
Dibutuhkan sistem pendataan nasional pengetahuan tradisional, semacam traditional knowledge digital library seperti yang dimiliki India.
Dengan ini, kita bisa memiliki bukti otentik bahwa pengetahuan tersebut telah lebih dulu eksis di masyarakat sebelum diklaim oleh pihak lain.
Sistem ini juga dapat menjadi alat perlindungan preventif terhadap paten yang diajukan tanpa dasar yang sah.
Bagi Pemerintah untuk Menyusun Regulasi Khusus tentang Perlindungan Pengetahuan Tradisional, yang Mencakup:
(1). Pengakuan hak kolektif masyarakat adat,
(2). Mekanisme prior informed consent sebelum pengetahuan dipakai pihak luar,
(3). Sistem benefit-sharing yang adil jika terjadi pemanfaatan komersial, dan
(4). Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pencurian hak.
Antara Komersialisasi dan Kedaulatan Pengetahuan
Melindungi pengetahuan tradisional bukan berarti menghambat inovasi. Justru sebaliknya, jika dikelola dengan adil, PT bisa menjadi fondasi inovasi berbasis lokal yang berdaya saing global.
Lihat saja geliat produk-produk lokal berbasis herbal yang mulai naik daun, dari jamu kemasan modern hingga kosmetik berbasis rempah.
Namun semua ini harus dikembalikan pada prinsip keadilan: masyarakat lokal sebagai pemilik pengetahuan harus dilibatkan dan diuntungkan, bukan sekadar menjadi objek eksotis yang dikomodifikasi.
Kedaulatan pengetahuan, pada akhirnya, adalah bagian dari kedaulatan nasional.
Ketika kita gagal melindungi pengetahuan tradisional, kita sejatinya membiarkan warisan budaya dan identitas bangsa dijajah dalam bentuk baru: kolonialisme intelektual.
Baca juga: Hukum Tata Negara Bukan Sekadar Teori: Mengapa Mahasiswa Harus Peduli?
Menemukan Jalan Tengah
Sama seperti polemik HAKI dalam rekayasa genetika, perlindungan pengetahuan tradisional juga butuh keseimbangan antara insentif ekonomi dan keadilan sosial.
Negara perlu hadir secara aktif, bukan hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai pelindung kepentingan masyarakat adat dan penjaga warisan budaya bangsa.
Kampus, LSM, komunitas lokal, dan sektor industri harus bergandengan tangan untuk membentuk ekosistem perlindungan yang hidup, dinamis, dan berbasis kearifan lokal.
Indonesia berada di persimpangan penting: menjadi bangsa yang membiarkan warisan leluhurnya dibajak, atau menjadi bangsa yang menjadikannya sebagai sumber kekuatan dan identitas di tengah percaturan global.
Sudah saatnya pengetahuan tradisional kita tidak hanya dihargai secara budaya, tetapi juga dilindungi secara hukum.
Penulis: Feri Novianto
Mahasiswa Jurusan Magister Ilmu Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia
Editor: Anita Said
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News