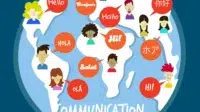Tradisi bukan hanya sekadar warisan masa lalu, tetapi juga representasi identitas kolektif yang membentuk jati diri suatu komunitas.
Dalam antropologi, tradisi dipahami sebagai simbol hidup dari sistem nilai, norma, dan struktur sosial yang terus mengalir dalam kehidupan masyarakat.
Salah satu tradisi yang kaya akan makna simbolik dan sosial adalah Nyongkolan, ritual pernikahan khas suku Sasak di Lombok, yang memadukan unsur estetika, spiritualitas, dan psikologi kolektif masyarakat.
Kata Nyongkolan berasal dari “songkol,” yang dalam dialek Sasak Petung Bayan berarti mendorong atau menggiring dari belakang.
Tradisi ini menjadi puncak prosesi pernikahan Sasak, di mana pasangan pengantin diarak dengan kemeriahan menuju rumah keluarga mempelai perempuan.
Lebih dari sekadar seremonial, Nyongkolan adalah deklarasi sosial: bahwa pasangan tersebut telah sah menikah dan kini menjadi bagian dari komunitas yang lebih luas.
Seorang informan lokal menyatakan bahwa Nyongkolan berfungsi sebagai bentuk “pengumuman” agar masyarakat tahu bahwa pernikahan telah berlangsung secara sah.
Dalam konteks ini, Nyongkolan menjadi media komunikasi kolektif antarwarga dan sekaligus sarana mempererat kohesi sosial.
Prosesi Nyongkolan berlangsung setelah tahap-tahap penting dalam pernikahan Sasak: mulai dari beberayean (masa berpacaran), merrariq (membawa lari mempelai perempuan), selabar (pemberitahuan pernikahan), hingga sorong serah aji krama (penyerahan simbol kekerabatan).
Nyongkolan sebagai tahap akhir adalah klimaks dari hubungan sosial dan budaya antar keluarga.
Pengantin dan para pengiring mengenakan busana adat penuh makna simbolik: wanita memakai baju lambung atau kebaya dengan kain songket dan sanggul, sementara pria mengenakan jas tegodek nongkeq, kereng selewoq poto, dan capuk khas Lombok.
Busana ini tidak hanya indah secara visual, tapi juga menyiratkan status, peran, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat.
Tradisi Nyongkolan memiliki prosesi yang unik dan meriah. Sepasang pengantin, seperti raja dan ratu sehari, diiringi oleh keluarga, pemuka adat, tokoh agama, serta warga desa lainnya yang mengenakan pakaian adat khas Sasak.
Iringan tersebut juga dimeriahkan dengan alat musik tradisional
Nyongkolan diiringi oleh gendang beleq, tambur, dan tawaq-tawaq, membangkitkan semangat kolektif yang kuat. Dalam perspektif psikologi budaya, tradisi ini menciptakan rasa bangga, keterikatan emosional, serta memperkuat identitas kelompok.
Arak-arakan ini bukan hanya perayaan, tetapi juga terapi kolektif—menumbuhkan solidaritas, rasa diterima, dan perlindungan sosial terhadap pasangan yang baru menikah.
Rangkaian tahapan, seperti pemuput selabar, nanggep, dan begawe menegaskan bahwa pernikahan dalam tradisi Sasak bukanlah urusan dua individu semata, melainkan institusi sosial yang melibatkan tanggung jawab kolektif antar keluarga dan komunitas.
Gotong royong, musyawarah, dan tolong-menolong menjadi etos utama yang menyatu dalam pelaksanaan tradisi ini tahapan prosesi dalam tradisi pernikahan Sasak yang berakhir pada Nyongkolan: (1) Beberayean atau masa berpacaran, (2) Merrariq, yaitu prosesi membawa lari calon mempelai perempuan, (3) Selabar, pemberitahuan resmi bahwa pasangan telah menikah, (4) Sorong Serah Aji Krama, yaitu penyerahan simbol kekerabatan, dan (5) Nyongkolan sebagai puncak perayaan.
Nyongkolan bukan sekadar ritual, melainkan narasi hidup masyarakat Sasak tentang cinta, keluarga, dan keberadaan sosial.
Ia mengajarkan bagaimana identitas budaya dibangun melalui simbol, bahasa, dan aksi kolektif yang diwariskan lintas generasi.
Dalam kacamata antropologi psikologis, tradisi ini menjadi arena tempat nilai-nilai seperti solidaritas, toleransi, dan tanggung jawab sosial tidak hanya diajarkan, tetapi juga dirasakan bersama.
Sebagai mahasiswa atau pemerhati budaya, memahami Nyongkolan berarti memahami cara kerja budaya dalam membentuk kepribadian sosial, dan bagaimana masyarakat menciptakan ruang untuk mempertahankan identitas sekaligus bernegosiasi dengan zaman.
Penulis:
1. Angela Maftukha A. (2023011071)
2. Mega Bunga Waluya (2023011073)
3. Aura Hapsari (2023011094)
4. Raafi’ud Nia Darajaatu (2023011097)
Mahasiswa Prodi Psikologi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Dosen pengampu: Hartosujono A.Md., S.E., S.Psi., M.Si
Daftar Pustaka
Herlina, L. (2023). PERSPEKTIF MAHASISWA MUSLIM FKIP UNIVERSITAS MATARAM TERHADAP AJARAN ISLAM DALAM TRADISI “NYONGKOLAN” SEBAGAI BAGIAN DARI PROSESI PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT SASAK LOMBOK. Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan, 536-548.
Kartika, Y. (2023). Tradisi Nyongkolan Di Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 18-21.
Lili Hernawati, M. D. (2020). Pergeseran Tradisi Nyongkolan Pada Proses Perkawinan Adat Suku Sasak di Kabupaten Mamuju Tengah. Sosioreligius, 28-35.
Muhammad Iwan Dani, N. P. (2024). Kajian Kritis Tradisi Nyongkolan dalam Perkawinan Adat Lombok Perspektif ‘Urf. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 73-84.
Putri Pertiwi, Aura Wastinaya, Sania Amalina, Anisa Septia Dini, Windaa Desi Partika Sari, Ni Made Ayu Amanda Indriani Putri. IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM PROSES NYONGKOLAN DI LOMBOK : KAJIAN BUDAYA DAN SOSIAL (2024). Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif, 11-17.
Triwahyudi, F. &. (2014). Makna Menarik dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin di Nusa Tenggara Barat. Jurnal Empati, 57-69.
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News