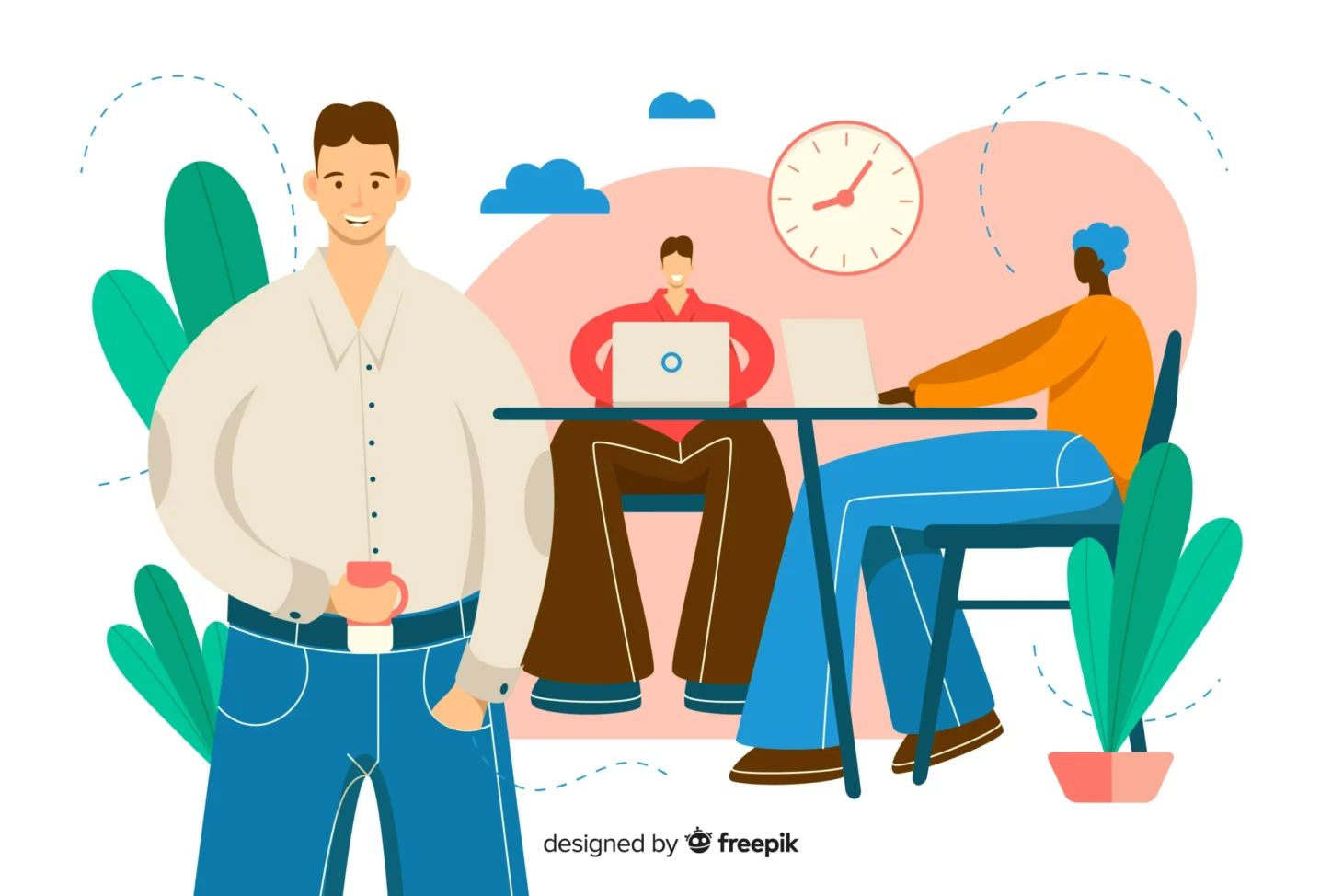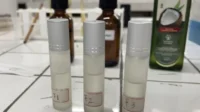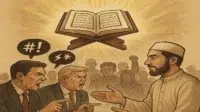Istilah Quiet Quitting belakangan ini kerap menjadi bahan perbincangan, terutama di kalangan pekerja muda.
Pernahkah kamu merasa lelah bekerja keras, namun apresiasi dan kesejahteraan tidak juga datang?
Atau mungkin kamu memperhatikan rekan kerja yang perlahan mulai menjaga jarak, tetap hadir di kantor, menyelesaikan tugas, namun enggan terlibat lebih jauh dari kewajiban formal?
Inilah yang disebut Quiet Quitting—fenomena yang diam-diam menjadi norma baru di dunia kerja, khususnya di kalangan generasi muda yang jenuh dengan budaya kerja berlebihan.
Meski istilahnya terkesan dramatis, Quiet Quitting sejatinya bukan soal mengundurkan diri dari pekerjaan, melainkan bentuk penolakan halus terhadap pola kerja berlebihan yang tidak seimbang dengan hak dan kesejahteraan.
Tren ini, yang banyak disuarakan di TikTok dan media sosial, menjadi sinyal bahwa generasi pekerja mulai mempertanyakan relasi kekuasaan yang selama ini mengakar di tempat kerja.
Dari sudut pandang Cultural Studies, Quiet Quitting bisa dibaca sebagai bentuk resistensi simbolik terhadap dominasi ideologi kapitalisme produktivitas, yang selama ini dipromosikan seolah-olah adalah sesuatu yang wajar.
Ketika “Kerja Cerdas” Disalahartikan Sebagai Kemalasan
Fenomena Quiet Quitting bukan tentang berhenti total dari pekerjaan. Ini adalah keputusan untuk tetap bekerja sesuai kontrak, tanpa tambahan lembur yang seringkali tidak dihargai, dan tanpa ikut dalam ambisi yang pada akhirnya lebih menguntungkan pihak atasan atau perusahaan besar.
Konsep hegemoni dari Antonio Gramsci (1971) sangat relevan untuk menjelaskan fenomena ini. Selama bertahun-tahun, budaya kerja keras tanpa batas diposisikan sebagai standar profesionalisme.
Loyalitas tanpa syarat, lembur tanpa kompensasi, bahkan sikap “pasang badan” untuk perusahaan, dianggap sebagai bentuk pengabdian yang sepatutnya dilakukan.
Kita tidak dipaksa untuk menerimanya, namun perlahan, ide itu diterima sebagai hal yang lumrah. Siapa yang menolak tunduk dianggap tidak memiliki etos kerja.
Kini, semakin banyak generasi muda yang mulai sadar bahwa membatasi diri bukan berarti malas, melainkan bentuk kesadaran untuk tidak terus-menerus dieksploitasi oleh sistem kerja yang tidak sehat.
Media Sosial dan Produksi Makna Baru tentang Kerja
Di titik ini, diskursus media berperan besar, seperti diuraikan Michel Foucault (1972).
Melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga Twitter, generasi muda membangun narasi alternatif.
Mereka menyuarakan bahwa hidup tidak seharusnya hanya berkisar di meja kerja. Ada hak atas waktu luang, kesehatan mental, dan hubungan sosial yang perlu dijaga.
Seiring narasi ini terus disebarkan dan diulang-ulang, lambat laun muncul norma baru: bekerja secukupnya adalah bagian dari hak, bukan tindakan tidak loyal.
Siapa Diuntungkan, Siapa Dirugikan?
Melihat lebih jauh, sebagaimana dijelaskan Stuart Hall (1997), Quiet Quitting bukan semata-mata perilaku individual, melainkan juga berkaitan dengan konstruksi identitas kelas pekerja.
Dalam sistem kerja yang selama ini berlaku, kelompok yang paling dirugikan adalah mereka yang berada di posisi rendah, generasi muda, atau pekerja yang sulit mengakses peluang promosi.
Quiet Quitting menjadi cerminan dari ketidakpuasan sekaligus penegasan bahwa mereka bukan sekadar “alat produksi”, melainkan individu yang berhak menentukan batas.
Diam-Diam Melawan, tapi Tetap Mengguncang
Quiet Quitting adalah contoh nyata dari resistensi budaya yang dikemukakan Dick Hebdige (1979). Bentuk perlawanan tidak selalu harus muncul dalam aksi besar atau demonstrasi terbuka.
Kadang, ia hadir dalam tindakan-tindakan kecil yang perlahan menggoyahkan tatanan yang dianggap mapan.
Generasi muda memang tidak turun ke jalan. Tapi dengan diam-diam menolak tunduk pada budaya kerja eksploitatif, mereka sedang berupaya menarik garis tegas untuk melindungi diri mereka sendiri.
Kerja Tidak Seharusnya Menjadi Alat Penindasan
Tulisan ini bukan ajakan untuk bermalas-malasan, melainkan ajakan untuk membuka mata bahwa selama ini, banyak praktik kerja yang dikemas dengan istilah “dedikasi” atau “profesionalisme”, namun nyatanya mengandung unsur penindasan yang dilegalkan.
Kita tidak bisa terus-menerus membenarkan lembur tanpa bayaran, loyalitas buta, atau ambisi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Jika terus dibiarkan, ketimpangan ini akan semakin mengakar.
Quiet Quitting menjadi pengingat bahwa setiap orang punya hak untuk menentukan batas. Dunia kerja seharusnya menjadi ruang untuk tumbuh, bukan ruang yang membunuh kreativitas dan kesehatan mental.
Budaya kerja yang lebih sehat bisa terwujud jika kita mau mempertanyakan norma yang ada, berani menolak ketimpangan, dan bersama-sama memproduksi makna baru tentang kerja yang lebih adil dan manusiawi—sebagaimana yang kini sedang diperjuangkan generasi muda lewat Quiet Quitting.
Penulis: Virana Mega Putri
Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dosen Pengampu: Dr. Merry Fridha Tri Palupi, M.Si.
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News