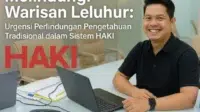Warisan budaya takbenda, seperti tari tradisional, merupakan bagian penting dari identitas nasional.
Di Indonesia, tarian-tarian tradisional mencerminkan kekayaan budaya yang sangat beragam dan sekaligus berpotensi menjadi sumber ekonomi.
Namun, di tengah arus globalisasi dan komersialisasi seni, muncul banyak persoalan seputar hak kekayaan intelektual (HAKI) dan klaim budaya antara pemerintah dan komunitas lokal.
Dalam konteks ini, menjadi penting untuk mengetahui siapa yang berhak atas kepemilikan tari tradisional dan bagaimana perlindungan hukum seharusnya diberikan.
Data dari Kemendikbud menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 300 tarian tradisional di Indonesia, masing-masing dengan nilai dan ciri khasnya sendiri.
Namun, tidak semuanya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menimbulkan dilema mengenai siapa yang berhak atas hak cipta dan bagaimana pengaturannya.
Masyarakat adat sebagai pencipta awal sering kali tidak memahami mekanisme hukum HAKI, sehingga hak mereka rentan diabaikan atau diambil pihak lain.
Permasalahan juga muncul ketika tarian dipertunjukkan di luar konteks budaya aslinya.
Contohnya, tari Saman yang sering dipentaskan di luar negeri tanpa melibatkan masyarakat Aceh sebagai pemilik budaya tersebut.
Hal ini memicu ketidakpuasan karena dianggap merugikan secara moral maupun ekonomi.
Oleh sebab itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum HAKI dapat digunakan untuk melindungi komunitas budaya dan memastikan mereka mendapat pengakuan yang semestinya.
Tujuan utama tulisan ini adalah menganalisis gesekan antara kepentingan budaya lokal dan nasional serta dampaknya terhadap komersialisasi seni tradisional.
Harapannya, dapat ditemukan pendekatan yang adil dan berkelanjutan untuk menjaga eksistensi budaya takbenda, terutama tari.
Secara umum, HAKI mencakup perlindungan seperti hak cipta, merek dagang, dan paten. Dalam kasus tarian, perlindungan melalui hak cipta paling relevan.
Namun, karena sifat tari tradisional yang diwariskan secara lisan dan tidak tertulis, sulit untuk membuktikan keasliannya menurut ketentuan hukum hak cipta yang berlaku.
Contoh nyata adalah tari Kecak dari Bali, yang sudah terkenal hingga mancanegara. Walau demikian, banyak penari dan seniman lokal yang merasa kontribusinya tidak diakui secara layak.
Studi Universitas Udayana menunjukkan bahwa lebih dari 70% pelaku seni Kecak tidak mengetahui hak mereka atas karya tersebut, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum terhadap eksploitasi.
UU No. 28 Tahun 2014 memang memberikan dasar hukum perlindungan karya seni, namun implementasinya menghadapi tantangan besar.
Sosialisasi masih minim, dan banyak masyarakat adat belum memahami prosedur pendaftaran atau pentingnya dokumentasi.
Hanya sekitar 5% dari keseluruhan tari tradisional yang telah terdaftar di DJKI.
Komersialisasi sering kali merusak makna budaya tari tradisional.
Banyak pihak yang menyesuaikan bentuk pertunjukan hanya untuk menarik minat penonton, mengabaikan nilai-nilai asli yang melekat pada tarian tersebut.
Ini mengundang pertanyaan tentang keaslian dan otentisitas pertunjukan.
Diperlukan sistem perlindungan yang tidak hanya berfokus pada hukum formal, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal secara aktif.
Edukasi tentang pentingnya HAKI serta partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian budaya harus menjadi prioritas.
Ketidaksepahaman antara komunitas lokal dan pemerintah kerap menimbulkan konflik budaya.
Pemerintah menganggap tarian tertentu sebagai milik nasional, sementara masyarakat adat merasa sebagai pemilik sah yang telah melestarikan tarian tersebut secara turun temurun.
Contoh nyata adalah tari Jaipong yang awalnya merupakan kreasi seniman lokal, tetapi saat ini diklaim sebagai bagian dari budaya nasional tanpa pemberian penghargaan yang layak kepada penciptanya.
Konflik semakin kompleks ketika tarian lokal dipentaskan di luar negeri tanpa keterlibatan masyarakat asalnya.
Hal ini juga terjadi pada tari Saman. Masyarakat Aceh merasa bahwa mereka tidak mendapat pengakuan maupun keuntungan dari pertunjukan tersebut.
Data menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Aceh tidak merasakan dampak ekonomi atau budaya dari komersialisasi tarian tersebut di luar negeri.
Komersialisasi seni tradisional di era global tak terhindarkan. Meski membawa peluang ekonomi, proses ini sering meminggirkan nilai-nilai budaya.
Misalnya, tari Piring dari Sumatera Barat kini lebih dikenal dalam bentuk pertunjukan turis daripada makna ritual aslinya.
Pergeseran ini menyebabkan berkurangnya nilai budaya dan spiritual.
Namun, ada juga contoh baik. Beberapa festival seperti Festival Kesenian Jakarta dan Festival Budaya Bali telah melibatkan komunitas lokal secara aktif dan memberikan manfaat langsung, baik secara ekonomi maupun budaya. Pendekatan semacam ini patut dijadikan model.
Untuk menjaga keberlanjutan budaya takbenda, khususnya tari tradisional, diperlukan strategi perlindungan yang inklusif.
Pemerintah perlu memperluas sosialisasi HAKI, melibatkan komunitas lokal dalam kebijakan, dan menciptakan dialog berkelanjutan antara semua pihak.
Dengan pendekatan kolaboratif dan adil, warisan budaya Indonesia bisa tetap lestari di tengah arus zaman.
Penulis: Bobby Rosseco
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News