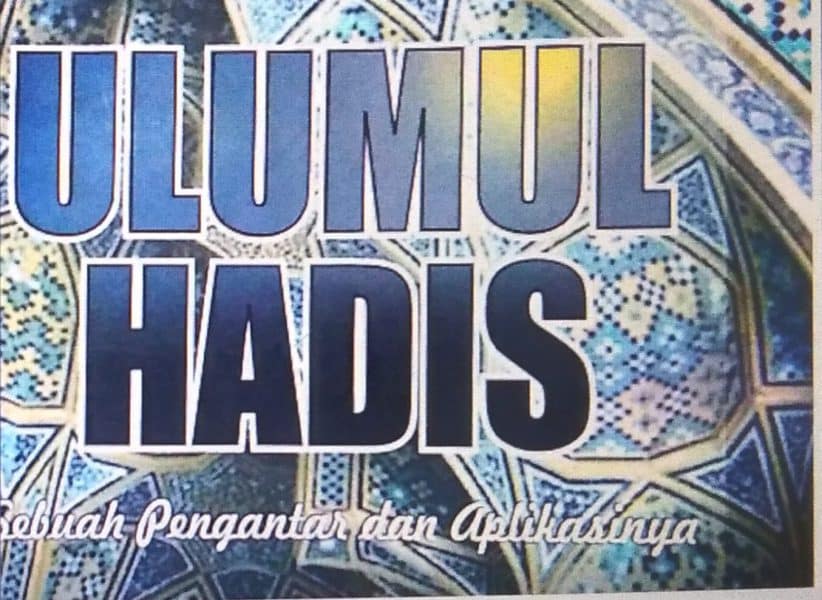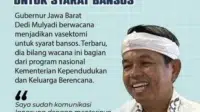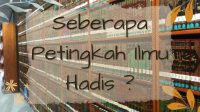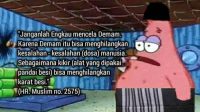Pendahuluan
Dalam kajian hadis mukhtalif, para ulama telah merumuskan teori atau ilmu yang berkaitan dengannya, yaitu ilmu Mukhtalif al-Hadis. Dengan memahami ilmu ini sesorang akan terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami hadis-hadis mukhtalif.
Ilmu mukhtalif al-hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang jika dilihat dari lahiriyahnya tampak bertentangan, baik bertentangan dalam arti berlawanan (bertolak belakang), atau dalam artian tidak sejalan (berbeda), yang bertujuan untuk menghilangkan pertentangan tersebut atau untuk menemukan pengkompromian antar hadis.
Biasanya akan terjadi kontradiksi antara dalil hadis dengan Al-Qur’an, hadis dengan hadis yang lain. Jika hal ini terjadi maka terdapat cara menyelesaiankannya.
Baca juga: Batasan-Batasan Makna Hadis
Dalam menetapkan cara penyelesaian hadis mukhtalaf yang dilakukan oleh para ulama, bukan berarti Al-Qur’an sebagai sumber pokok ajaran Islam yang mengalami kekeliruan penyampaian akan tetapi terdapat pemahaman makna majas atau karena terdapat unsur mutasyabihpada ayat Al-Qur’an yang harus dikaji secara mendalam berdasarkan kaidah uslub.
Dalam kesempatan ini penulis akan membahas tentang pengertian, syarat-syarat kategori mukhtalaf al-hadis, metode penyelesaian mukhtalaf al-hadis dan contoh.
Pembahasan
A. Pengertian Mukhtalif al-Hadis
Mukhtalif al-hadis, adalah istilah yang dalam ilmu hadis memiliki beberapa sinonim, seperti Ikhtilaf al-hadis, Musykil al-hadis, Ta’arudh al-hadis, dan Talfiq al-hadis.
Mukhtalif artinya yang bertentangan, yang berselisih atau kontradiktif. Dari sisi terminologi, istilah Mukhtalif atau Ta’arud menurut al-Zarkasi didefinisikan sebagai :
تقابل الدليلين على َسبِيْل الممانِعة
“Perbandingan dua dalil dengan cara saling menghalangi (bertolak belakang).”
Adapula yang memaknai Mukhtalif dengan:
تقابل الأَمريْن َيَمنَع ُكل ِمنْهما مقتضى صاحبه
“Perbandingan dua hal atau perkara, di mana masing-masing pernyataannya saling bertentangan.”[1]
Pertentangan dapat terjadi dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- Hukum yang ditetapkan oleh dua teks saling berlawanan, seperti halal dan
haram, wajib dan tidak wajib. - Obyek (tempat) kedua hukum yang saling bertentangan itu sama. Apabila
obyeknya berbeda maka tidak ada pertentangan. - Masa atau waktu berlakunya hukum sama. Karena mungkin saja terdapat
dua ketentuan hukum yang bertentangan dalam obyek yang sama, namun
masa atau waktunya berbeda. Seperti dihalalkannya menggauli istri
sebelum dan setelah masa menstruasi, namun diharamkan menggaulinya
dalam masa menstruasi.[2]
Adapun definisi dari Mukhtalif al-Hadis adalah:
هو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطلا أو تعارض مع نص شرعي أخر[3]
“ Hadis-hadis yang lahirnya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan nas syara’ yang lain.”
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mukhtalaf al-hadis secara sederhana bisa dimaknai dengan kontradiktifitas hadis. Maksudnya, hadis-hadis yang dari sisi teks atau redaksi maupun kandungannya terkesan kontradiktif atau tampak bertentangan.
Pertentangan dalam hadis dapat terjadi apabila terdapat hadis yang terkesan bertolak belakang dengan ayat Al-Qur’an yang sudah jelas pengertiannya, atau tampak berseberangan dengan hadis lain yang sederajat kualitasnya, bahkan juga apabila hadis tampak bertentangan dengan nalar.
Baca juga: Mengenal Sejarah Ilmu Hadist
1. Kontradiksi Hadis dengan al-Qur’an
Bila hadis telah memperoleh penilaian maqbul, namun konsep yang dikandung diduga berlawanan dengan petunjuk Al-Qur’an, maka rumusan konsep hadis harus berpihak pada eksplisitas Al-Qur’an. Berbeda jika konsep yang berasumsi kontroversial itu sama-sama berasal dari ungkapan hadis dan ayat yang ber-dalalah zanni karena unsur mutasyabih (metaforis), bangunan konsep sebaiknya diarahkan ke ta’wil (interpretasi
alegoris).
2. Kontradiksi Hadis dengan Hadis Lain
Dugaan kontradiksi antara kandungan makna hadis yang sederajat tidak jarang terjadi. Untuk tujuan merumuskan konsep doktrin versi hadis para ulama menawarkan solusi dengan metode kompromi al-jam’ dan bila dipandang perlu beberapa ulama menempuh upaya al-naskh dan al-tarjih.
3. Kontradiksi Hadis dengan Nalar
Sebagian ulama berpendapat bahwa temuan indikasi perlawanan antara subtansi kandungan matan hadis dengan penalaran, pada dasarnya ditandai dengan kelemahan pada sektor sanad, tepatnya pada kadar
kejujuran atau ketidak cermatan salah seorang periwayat dalam mata rantai sanad hadis. Sepanjang kualitas sanad hadis tersebut sahih, pasti dapat dijamin nilai kebenaran segala hal yang iinformasikannya. Kebenaran hipotesa bisa terlihat jelas pada sikap penerimaan ahli hadis pada matan hadis yang mengungkap hal-hal yang sifatnya supra rasional, yakni bidang akidah, berobjek hal-hal gaib.[4]
Para ulama hadis sejak masa klasik telah memberikan perhatian-perhatian yang serius terhadap masalah tersebut. Bahkan jauh sebelum ilmu-ilmu hadis dibukukan secara komprehensif, Ibn Qutaibah al-Dainuri (w. 276 H) juga mengkaji masalah tersebut dalam kitabnya Ta’wil Mukhtalaf al-Hadis, tetapi hanya sedikit hadis-hadis yang berindikasi kontroversial, sekitar 66 hadis, yang ia bahas dalam karyanya tersebut.[5]
Kemudian al-Nahawi (w. 321 H) dalam karyanya Musykil al-Atsar yang mengulas sekitar 323 hadis yang tampak bertentangan.[6] Selain itu masih ada beberapa ulama lainnya yang juga memberikan perhatian khusus terhadap hadis-hadis yang dinilai kontroversial, misalnya Ibn Faurak (w. 406 H) dengan bukunya yang berjudul Musykil al-hadis wa Bayanuh,[7] Ibn al-Jauzi (w. 597 H) dengan karyanya yang diberi judul al-Tahqiq,[8] serta beberapa ulama lainnya.[9]
B. Metode Penyelesaian Mukhtalif al-Hadis
Ulama hadis sepakat bahwa hadis-hadis yang tampak bertentangan harus diselesaikan, sehingga tidak ada lagi yag terkesan kontradiktif. Akan tetapi dalam menyelesaikan pertentangan tersebut, para ulama menempuh cara yang relatif berbeda.
Al-Syafi’i (w. 204 H), ulama yang menjadi pelopor dihimpunnya hadis-hadis yang terkesan bertentangan serta alternatif penyelesaiannya, menguraikan bahwa mungkin saja matan-matan hadis yang terkesan bertentangan mengandung petunjuk bahwa salah satu matan bersifat global (mujmal) dan yang lainnya bersifat detail (mufassar), ada pula kemungkinan matan hadis yang satu bersifat umum (‘amm) dan yang satunya bersifat spesifik (khas), selain itu bisa jadi matan hadis yang satu berperan sebagai “penghapus” (al-nasikh) terhadap matan hadis yang lain (al-mansukh) atau mungkin keduanya menunjukkan kebolehan untuk diamalkan.[10]
Dari uraian tersebut terlihat bahwa al-Syafi’i membicarakan masalah ini dari dua sisi; sisi yang pertama yaitu perbedaan signifikasi (dalalah) riwayat-riwayat, dan yang kedua perbedaan praktik yang ditransmisikan dari para sahabat. Dalam menyelesaikan “pertentangan” matan hadis, al-Syafi’i menggunakan mekanisme al-jam’kemudian al-naskh.
Berbeda dengan metode al-Syafi’i di atas, ulama Hanafiah umumnya lebih mengedepankan metode al-naskh dibanding altarjih dan al-jam’ serta al-tauqif.
Baca juga: Pentingnya Asbabul Wurud dalam Ilmu Hadis
Argumentasi Hanafiah yang mengedepankan metode penyelesaian seperti urutan di atas adalah karena al-naskh berarti mengamalkan dalil yang nasikh dan meninggalkan dalil yang mansukh. Metode al-naskh bukan hasil ijtihad seperti al-tarjih maupun al-jam’ tetapi merupakan hak prerogatif Allah SWT.
Metode al-tarjih didahulukan dari al-jam’ karena dengan metode tersebut dalil yang lebih kuat diutamakan dibanding dalil lain yang argumennya tidak sekokoh yang pertama.[11]
Ibn Hazm (w. 456 H) secara tegas menyatakan bahwa matan-matan hadis yang bertentangan, masing-masing harus diamalkan. Ia menekankan pentingnya penggunaan metode istisna’ (pengecualian) dalam menyelesaikan hal tersebut. Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H) menggunakan metode altarjih (memilih matan yang memiliki argumen yang lebih kuat).[12] Penggunaan metode tersebut tidak terlepas dari penerapan al-jam’ ataupun al-naskh.
Selain itu, beberapa ulama lainnya juga menggunakan metode yang hampir sama, meskipun dengan urutan yang berbeda. Al-Tahawani, misalnya, menempuh cara al-naskh kemudian al-tarjih. Shalah al-Din ibn Ahmad al-Adlabi menyelesaikan pertentangan matan-matan hadis dengan cara al-jam’kemudian al-tarjih.
Ibn Shalah (w. 643 H) dan Fasih al-Harawi (w. 837 H), menggunakan tiga alternatif penyelesaian, yakni al-jam’, al-naskh, dan al-tarjih. Yusuf al-Qardhawiy, sama halnya dengan Ibn Shalah dan al-Harawi, juga menawarkan metode al-jam’, al-naskh, dan al-tarjih sebagai tahapan penyelesaian hadis yang tampak bertentangan. Hanya saja, walaupun ia tidak menjelaskan secara menyeluruh, ia terkesan tidak menyetujui metode al-naskh, dan al-tarjih.
Ketika menjelaskan ketiga metode tersebut, al-Qardhawi tidak memberikan contoh untuk kedua metode yang terakhir. Muhammad ‘Adib Shalih menempuh cara al-jam’, al-tarjih, kemudian al-naskh. Ibn Hajr al- ‘Asqalani (w. 852 H) menempuh empat tahapan, yakni: al-jam’, al-naskh, al-tarjih, dan al-tauqif.[13]
Syuhudi Ismail menanggapi perbedaan metode yang digunakan para ulama dalam upaya menyelesaikan hadis yang terkesan bertentangan, beliau menganggap tawaran yang diajukan oleh al-‘Asqalani lebih akomodatif. Beliau juga menilai keempat tahap atau cara itu dapat memberikan alternatif
yang lebih hati-hati dan relevan.[14]
Walaupun metode maupun tahapan penerapan metode yang ditawarkan ulama berbeda-beda, namun Syuhudi Ismail memandang tidak harus berbeda dalam penyelesaiannya. Mengapa demikian? karena para ulama pada umumnya mengutamakan metode al-jam’ selama metode tersebut dapat diterapkan, selain itu metode penyelesaian yang diberi istilah yang berbeda, ternyata hasilnya banyak yang menunjukkan kesamaan.[15]
Berikut merupakan beberapa metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan mukhtalif al-hadis:
1. Al-Jam’ (al-Taufiq atau al-Talfiq)
Secara sederhana al-jam’ dapat diartikan dengan mengkompromikan. Maksudnya, mencari benang merah antara hadis-hadis yang terkesan kontradiktif sehingga bisa ditemukan titik kompromi yang menyebabkan hadis-hadis tersebut tidak bertentangan lagi. Dalam al-jam’, hadis-hadis yang tampak kontradiktif tersebut dipahami dengan mempertimbangkan bentuk dan cakupan petunjuk hadis yang bersangkutan, fungsi Nabi ketika hadis itu muncul, dan peristiwa yang melatarbelakangi hadis tersebut.[16]
Menurut al-Syafi’i untuk menerapkan metode al-jam’, harus didasari pemahaman yang memadai tentang kaidah-kaidah Ushul Fiqh, konteks (asbab al-wurud) dari masing-masing hadis yang tampak kontradiktif, korelasi hadis-hadis yang terkesan bertentangan dengan hadis-hadis lainnya, dan cara mentakwil salah satu hadis kepada makna yang lebih sesuai atau sejalan dengan makna hadis yang lainnya.
2. Al-Naskh
Secara etimologi, al-naskh mempunyai dua pengertian, yaitu al-izalah (menghilangkan) dan al-naql (menyalin). Sedangkan secara terminologi, terdapat perbedaan pengertian oleh para ulama’. Ulama’ Mutaqaddimiin, ulama abad I hingga III H, memperluas arti naskh hingga mencakup: pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar, dan penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.[17]
Pengertian itu kemudian diciutkan oleh para ulama mutaakhkhiriin yang membatasi naskh pada ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir.[18]
Berdasarkan pengertian tersebut, bila dikaitkan dengan mukhtalif al-hadis, dapat diambil kesimpulan bahwa apabila diketahui salah satu dari hadis-hadis yang tampak bertentangan itu muncul lebih dahulu, maka hadis yang dahulu itu dinyatakan di naskh oleh hadis yang lahir belakangan.[19]
Naskh merupakan sebuah proses logis dan dibutuhkan dalam penerapan teks-teks yang tepat dan menunda penerapan teks yang lain sampai saat memungkinkan penerapan teks itu tiba.[20]
Jika al-naskh dimaknai dengan pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu karena kondisi yang berbeda, maka penggunaan pengertian naskh seperti itu, sesungguhnya merupakan bagian dari bentuk al-jam’.
Karena, hadis yang tidak berlaku lagi bagi masyarakat tertentu, tetap bisa berlaku bagi masyarakat lain yang kondisinya sama dengan kondisi semula.[21]
3. Al-Tarjih
Al-Tarjihadalah memilih salah satu tetapi bukan dengan cara al-naskh, tetapi meneliti “kekuatan” dan “kelemahan” masing-masing hadis. selanjutnya dipilih hadis yang dinilai memiliki argumen yang lebih kuat dibanding hadis yang lain. Metode ini disebut dengan al-tarjih. Untuk melakukan al-tarjih, terdapat metode-metode khusus yang jumlahnya cukup banyak. Al-Hazimi menyebutkan sebanyak 50 macam, sedang Ibnu Shalah menetapkan hingga lebih dari 100 macam metode. Namun, al-Suyuti menawarkan metode yang lebih ringkas, yaitu:
- Tarjih berdasarkan keadaan periwayat dalam segala aspeknya, di antaranya:
- Tarjih berdasarkan jumlah periwayat dalam transmisi hadis.
- Tarjih berdasarkan kedhabithan periwayat.
- Tarjih berdasarkan integritas moral periwayat.
- Tarjih dengan melihat proses tahammul hadis.
- Tarjih dengan memperhatikan cara periwayatan.
- Tarjih dengan mengacu pada waktu wurud (disabdakannya hadis). Namun, menurut al-Razi (w. 327 H), tarjih dengan cara ini tidak kuat.
- Tarjih dengan mempertimbangkan redaksi hadisnya, seperti memilih hadis yang bersifat khusus daripada yang umum.
- Tarjih dengan merujuk pada hukum yang terkandung dalam hadis
tersebut. - Tarjih dengan memperhatikan faktor eksternal dari hadis tersebut. Seperti mendahulukan hadis yang sesuai dengan makna zahir dari al-Qur’an atau hadis lain. [22]
Dalam metode al-tarjih rentan terhadap unsur “pengabaian” atas hadis-hadis yang berdasarkan hasil penelitian dinilai shahih.
Hasil dari metode ini adalah ditentukannya salah satu hadis yang dinilai memiliki kualitas ilmiyah yang tinggi di banding hadis-hadis lainnya sebagai dasar syariat Islam. Dengan demikian, hadis lain yang kualitasnya dianggap lebih rendah meskipun hadis tersebut sahih akan “terabaikan”.
4. Al-Tauqif
Al-Tauqif pada dasarnya bukan metode. Menurut sebagian ulama al-tauqif merupakan langkah terakhir jika semua metode sudah ditempuh namun tidak ditemukan solusi atas pertentangan matan hadis yang diteliti.
Hadis-hadis kontroversial tersebut ditunda untuk diteliti, dibiarkan saja, sampai bisa ditemukan tanda-tanda yang dapat dijadikan acuan, baik indikasi al-jam’, al-naskh, maupun al-tarjih.
Kesimpulan
Mukhtalif al-hadis adalah hadis-hadis yang dari sisi teks atau redaksi maupun kandungannya terkesan kontradiktif (tampak bertentangan).
Pertentangan dalam hadis dapat terjadi apabila terdapat hadis yang terkesan bertolak belakang dengan ayat Al-Qur’an yang sudah jelas pengertiannya, atau tampak berseberangan dengan hadis lain yang sederajat kualitasnya, bahkan juga apabila hadis tampak bertentangan dengan nalar.
Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan mukhtalif al-hadis: 1) Al-Jam’ (al-Taufiq atau al-Talfiq) yaitu mengkompromikan. Maksudnya, mencari benang merah antara hadis-hadis yang terkesan kontradiktif sehingga bisa ditemukan titik kompromi yang menyebabkan hadis-hadis tersebut tidak bertentangan lagi. 2) Al- Naskh yaitu sebuah proses logis dan dibutuhkan dalam penerapan teks-teks yang tepat dan menunda penerapan teks yang lain sampai saat memungkinkan penerapan teks itu tiba. 3) Al-Tarjih yaitu memilih salah satu tetapi bukan dengan cara al-naskh, tetapi meneliti “kekuatan” dan “kelemahan” masing-masing hadis. selanjutnya dipilih hadis yang dinilai memiliki argumen yang lebih kuat dibanding hadis yang lain. 4) Al-Tauqif, pada dasarnya bukan metode. Menurut sebagian ulama al-tauqif merupakan langkah terakhir jika semua metode sudah ditempuh namun tidak ditemukan solusi atas pertentangan matan hadis yang diteliti.
Penulis: Nur Azizah
Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Daftar Pustaka
Dr. H. Muhammad yahya, M. Ag. Ulumul Hadis Sebuah Pengantar dan Aplikasinya,Syahadah desember 2016.
www.pesantren.or.id. Dengan judul Hadith Kontradiktif dan Solusinya.
‘Itr, Nur al-Din. Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis. Cet. III; Damaskus: Dar al-Fikr, 1992.
Abbas, Hasjim, Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha, Cetakan I; Yogyakarta: Teras, 2004.
Al-Dainuri, ‘Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah. Ta’wil Mukhtalaf al-Hadis (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).
al-Nawawi, Abu Ja’far. Musykil al-itsar. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1995.
Rahman, Fathur. Ikhtishar Musthalah al-Hadis. Bandung: PT al-Ma’arif, 1974.
Yaqub, Ali Mustafa, Kritk Hadis, Cet. I, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.
Hasbi ash Shiddieqy, Tengku Muhammad, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis . Cet. IV; Semarang: PT. Pustaka Rezki Putra, 1999.
Yaqub, Ali Mustafa Kritik Hadis Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi (al-Qasimi), Qawa’id al-Tahdits: Min Funun Mustalah al-hadis . Mesir: ‘Isa al-Babi al-Halabi, 1971.
Arifuddin Ahmad; Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Refleksi pemikiran Pembaharuan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail). (jakarta : MSCC. 2005).
Al-Syatibi. al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, Juz II. Cet. II; Beirut: Dar al-Ma’arif, 1975.
Yoesqi, Moh. Isom. Inklusivitas Hadis Nabi Muhammad saw. Menurut Ibn Taimiyyah Cet. I; Jakarta: Pustaka Mapan, 2006).
Aly MD, Achmad. Teori Naskh Mahmud M. Nuha dan Nashariyat al-Hudud Muhammad Syahrur: Telaah Komparatif dengan Paradigma Maqasid alSyari’ah”. Eds. Udjang Thalib, Yusuf Rahman dkk. Indo Islamika : Journal at Islamic Sciences. Vol. 4, no. 2, 2007.
Shihab, Quraish, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Cet. VII; Bandung: Mizan, 1994).
Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi,Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi (Beirut: Dar Ihya’ alSunnah al-Nabawiyyah, t.th).
[1] Dr. H. Muhammad yahya, M. Ag, Ulumul Hadits Sebuah Pengantar dan Aplikasinya,Syahadah desember 2016, hal 181
[2] Dikutip dari www.pesantren.or.id. Hadith Kontradiktif dan Solusinya.
[3] Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis (Cet. III; Damaskus: Dar al-Fikr, 1992), hal. 337
[4] Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis : Versi Muhaddisin dan Fuqaha (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2004), hal. 113-124.
[5] ‘Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah al-Dainuri, Ta’wil Mukhtalaf al-Hadits (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).
[6] Ab Ja’far al-Nawawi, Musykil al-atsar (Cet. I; Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiyyah, 1995).
[7] Fatchur Rahman, Ikhtishar Mushthalahu’l Hadits (Cet. I; Bandung: PT. Alm’arif, 1974), hal. 339.
[8] T.M. Hasbi ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits (Cet. IV; Semarang: PT. Pustaka Rezki Putra, 1999), hal. 143.
[9] Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis (Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal. 90-91.
[10] M. Syuhudi Ismail, Metodologi… op. cit., hal. 143. Lihat juga Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi (al-Qasimi), Qawa’id al-Tahdits: Min Funun Mustalah al-hadits (Mesir: ‘Isa al-Babi al-Halabi, 1971), hal. 308- 313.
[11] Moh. Isom Yoesqi, Inklusivitas Hadits Nabi Muhammad saw. Menurut Ibn Taimiyyah (Cet. I; Jakarta: Pustaka Mapan, 2006), hal. 162.
[12] M. Syuhudi Ismail, log. cit.
[13] Ibid., hal. 143-144.
[14] Ibid., hal. 144.
[15] Ibid. hal. 144-145
[16] Arifuddin Ahmad, op. cit., hal. 118
[17] al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, juz II (Cet. II; Beirut: Dar al-Ma’arif, 1975), hal. 107-108.
[18] M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Cet. VII; Bandung: Mizan, 1994), hal. 144.
[19] Ali Mustafa Yaqub, op. cit., hal. 94.
[20] Achmad ‘Aly MD, “Teori Naskh Mahmud M. Nahi dan Nasyariyat al-Hudud Muhammad Syahrur: Telaah Komparatif dengan Paradigma Maqasid al-Syari’ah”, eds. Udjang Thalib, Yusuf Rahman, dkk., Indo Islamika, vol 4, no 2, 2007, hal. 254-256.
[21] Arifuddin Ahmad, op. cit., halm. 118.
[22] Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi,Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi (Beirut: Dar Ihya’ alSunnah al-Nabawiyyah, t.th), hal. 197-198.